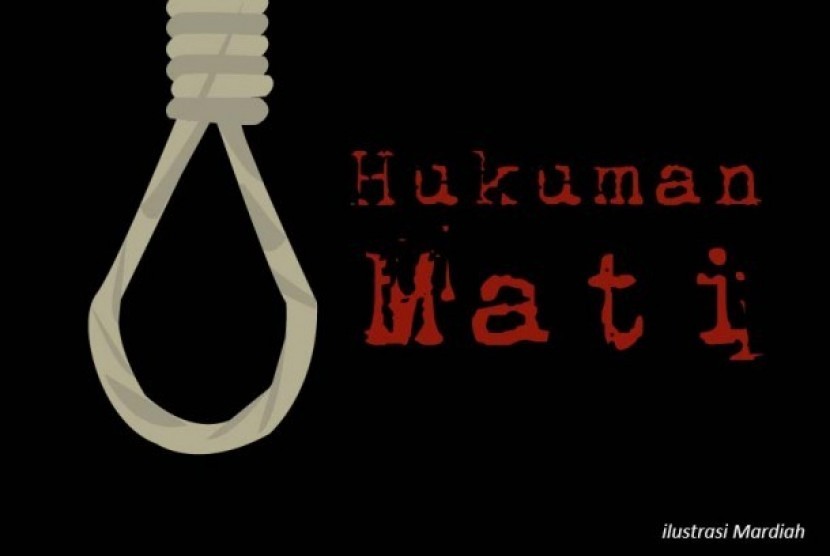REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mewacanakan hukuman mati terhadap koruptor Jiwasraya maupun Asabri. Terkait wacana hukuman mati koruptor Jiwasraya-Asabri, Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Universitas Pakuan Bogor, Yenti Garnasih mengatakan bahwa terkait dengan pidana mati, menurutnya bukanlah kewenangan jaksa agung. Kejaksaan hanya bisa melakukan penuntutan, namun yang memutuskan adalah majelis hakim.
"Kalau pidana mati itu kan urusannya bukan di jaksa agung, urusannya di hakimnya. Jaksa hanya menuntut kan, tapi apakah nanti bisa dilaksanakan atau tidak, atau dijatuhkan atau tidak itu tergantung hakim," kata Yenti, Sabtu (30/10).
Menurutnya, pidana mati memiliki sejumlah risiko yang harus diperhitungkan secara matang. "Kita harus berhitung kalau seandainya uang para koruptor itu di luar negeri, nah itu ada perhitungannya tuh. Artinya kemungkinan kita agak susah meminta bantuan kepada negara lain, tolong rampaskan uang-uang koruptor ini, kecuali negara itu juga menerapkan pidana mati," katanya.
"Misalnya Indonesia menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi, harta kekayaannya ada di Malaysia atau Singapura yang juga menerapkan hukuman mati sebagaimana beberapa negara yang juga demikian, kita minta bantuan ke sana itu oke saja," katanya.
"Tapi kalau kita menerapkan pidana mati dan harta kekayaan yang disita ini belum selesai proses perampasannya dan kita minta tolong ke negara yang tidak menganut pidana mati biasanya ditolak. Karena 'nggak bisa, kan negara saya dan negara anda berbeda prinsip karena kami tidak lagi menganut pidana mati, namun negara anda menganut pidana mati'," ujarnya lagi.
Seharusnya dipahami bahwa kasus korupsi tidak hanya pada tindak pidananya saja, namun juga terkait erat dengan penyitaan aset hasil dari tindak pidana korupsinya seoptimal mungkin. Namun, kata dia, jaksa juga harus cermat dalam melakukan penyitaan atau perampasan, sehingga tidak ada pihak lain yang dirugikan.
"Hal itu memang benar-benar harus dilakukan secara transparan kepada masyarakat, yang udah disita itu berapa, gitu. Harus dikaitkan juga dengan proses penyitaannya, karena kan kemarin ada pihak ketiga yang beritikad baik dimenangkan gugatannya. Jadi sebaiknya proses penyitaannya harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat, bagaimana sebetulnya gitu loh. Jadi jangan kita gebar-geber di proses penyitaannya saja tapi jumlahnya berapa dan apakah betul itu milik tersangka atau dibeli oleh tersangka dengan uang korupsi?" kata Yenti.
Selain pemidanaan bertujuan untuk penjeraan, Yenti mengatakan bahwa yang tak kalah penting adalah pencegahan tindak pidana korupsi. "Jadi perlu kerjasama semua pihak, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jangan membuat sistem yang membuat orang mau korupsi. Kita jangan hanya melihat orang korupsi di pidana mati, dipenjarakan, dibuat jera, itu tidak bisa! Jadi kita sudah saatnya harus bicara juga tentang pencegahan tindak pidana koruspi secara sitematis, dan melihat sistem-sistem yang ada di eksekutif, yudikatif dan legislatif," lanjutnya.
"Sebenarnya kalau jaksa menuntut setinggi-tingginya pidana mati, oke saja. Tapi kalau ngomong jaksa akan menghukum pidana mati itu, ya nggak bener. Nggak mungkin mereka menghukum kan? Jaksa hanya bisa menuntut setinggi-tingginya," kata Yenti.
Ia pun mengatakan bahwa seluruh pemangku kebijakan juga harus berkomitmen dalam melakukan penegakan hukuman mati bila nanti akhirnya disepakati, jangan sampai lembaga-lembaga terkait tak sejalan. "Nanti hakimnya malah bertolak belakang," kata Yenti yang juga tim perumus RUU KUHP.
Yenti menyebut jika RUU KUHP disahkan, nantinya mekanisme hukuman mati akan berubah. "Pidana mati itu merupakan pidana khusus, pidana mati itu tidak langsung dilakukan seperti sekarang ini. Tapi pidana mati itu baru akan dilaksanakan bila 'inkracht'nya telah 10 tahun. Jadi bila sekarang dijatuhkan pidana mati, itu ada waktu 10 tahun untuk menilai kembali. Setelah 10 tahun, baru akan diputuskan 'oke pidana mati atau akan berubah' gitu, jadi pidana mati yang tertunda atau pidana mati percobaan," lanjutnya.
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pun ikut mengkritisinya. Menanggapi hal itu, Staf Divisi Advokasi KontraS Tioria Pretty mengatakan bahwa hukuman mati bukanlah cara efektif untuk membuat jera para koruptor, sebab tak ada bukti empirik terkait hal itu.
Sehingga menurutnya hukuman mati bukan menunjukkan ketegasan dalam penegakan hukum di Indonesia. "Dari awal soal hukuman mati baik itu terhadap korupsi atau tindak pidana lainnya, sejauh ini tidak ada bukti empirik yang dapat membuktikan pemberlakuan pidana mati efektif dalam memberikan efek jera dan menurunkan tingkat kejahatan," ujar Pretty.
Kondisi itu didukung dengan masih adanya permasalahan besar dalam menciptakan sistem peradilan yang adil (fair trial) di Indonesia. Pretty mengatakan bahwa pihaknya kerap menemukan berbagai perlakuan tidak adil seringkali diterima oleh terpidana mati.
"Seperti kualitas pendamping hukum yang buruk, kurangnya akses penerjemah yang berkualitas, pengakuan-pengakuan yang terlontar karena adanya paksaan yang kemudian dijadikan bukti dalam proses persidangan, dan akses terbatas menuju banding, peninjauan kembali dan prosedur grasi. Jadi sekali lagi hukuman mati bukanlah alat untuk menunjukkan ketegasan penegakan hukum," katanya.