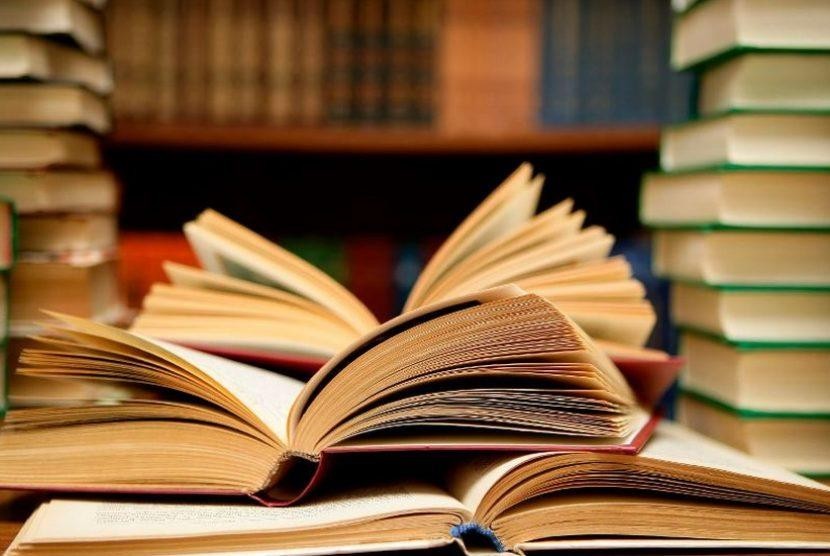Di tengah malam dalam mimpinya, Khalifah Abbasiyah Al-Ma’mun, putra Khalifah Harun Ar-Rasyid, didatangi seseorang yang berpakaian rapi dan berjanggut panjang. Orang tersebut tiba-tiba tanpa pengantar memperkenalkan diri berbicara seputar filsafat dengan bahasa asing dan aneh, yang anehnya pula Al-Ma’mun langsung mampu memahami apa yang diutarakannya.
Keduanya pun asyik larut berdiskusi topik-topik yang dalam studi agama kontemporer dikenal dengan teologi (Tuhan), kosmologi (alam) dan antropologi (manusia). Ketika terbangun, Al-Ma’mun menerka orang bijak itu pastinya adalah Aristoteles.
Entah mendapat pesan khusus apa, segera ia mengumpulkan para ilmuwan dan intelektual untuk mendirikan sebuah perpustakaan yang kelak dikenal dengan nama Khizanat Al-Hikmah, yang di dalamnya terdapat Bait Al-Hikmah, sebuah pusat studi keunggulan untuk dilakukannya penterjemahan besar-besaran buku-buku Yunani, Romawi, Persia, hingga India.
Para ilmuwan dan intelektual tersebut dikirim ke berbagai kota di wilayah-wilayah Bizantium untuk memulai perjalanan mencari dan mengumpulkan karya-karya Aristoteles dalam bahasa Yunani untuk dibawa ke Baghdad. Dimulailah proses penerjemahan dan pemberian catatan yang dilakukan oleh para ilmuwan seperti Sahl ibn Harun yang sekaligus sebagai direktur Bait Al-Hikmah, Musa Al-Khawarizmi (matematika dan astronomi), Abu Sahl ibn Nawbah (sastra Persia), Abdullah ibn Al-Muqaffa (sastra) menterjemah karya filosof India, Baidaba dengan Kalilah wa Dimnah-nya, Abu Yahya ibn Al-Batriq (filsafat) menerjemah Historia Animalum dan Politica-nya Aristoteles dan Tetrabilosnya Ptolemy atas permintaan khusus Khalifah, Hasan ibn Sahl As-Sarakhsi (kedokteran) menerjemah karya-karya Hippocrates dan Galen.
Masing-masing rumpun ilmu mempunyai tim dan anggotanya sendiri. Baghdad sebagai Ibukota Dinasti Abbasiyah pun menjadi kota metropolis yang dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan yang pada suatu masa di dalamnya terdapat kurang lebih 36 perpustakaan dengan jumlah koleksi sekitar 360.000 buku dan manuskrip. Belum lagi ditambah koleksi perpustakaan pribadi seperti sejarawan Al-Waqidi, yang konon koleksinya tidak cukup diangkut dengan 600 ekor unta.
Dampak lain adalah iklim masyarakat yang mencintai ilmu pengetahuan dan pengembangannya, terutama mencintai buku, hingga seorang Al-Mutanabbi (penyair masyhur) yang mengalami suasana Baghdad saat itu bersyair, “Khairu jalisin fi kulli zaman kitabun” (buku adalah sahabat terbaik manusia sepanjang waktu).
Pertanyaannya, mengapa Al-Ma’mun dan para pendiri awal Dinasti Abbasiyah bersusah payah membangun institusi Khizanat Al-Hikmah? Dimitri Gustas, sejarawan dari Universitas Yale dalam Greek Thought, Arabic Culture. The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early ‘Abbasid Society (2nd-4th / 8th-10th centuries) (Routledge: London-NY, 1998) menjawab, tidak lain karena pengaruh sistem administrasi peradaban dinasti-dinasti Sasanian Persia yang mengharuskan adanya suatu institusi pusat arsip nasional suatu bangsa, yang merekam dinamika keilmuan bangsa tersebut, juga sebagai simbol kebanggaan dan identitas suatu bangsa yang besar dan maju.
Agar tidak terjebak dan sebagai obat rutinitas administratif dan konflik-konflik melelahkan. Di era modern, hal itu dilakukan oleh Amerika dengan Library of Congress-nya sebagai perpustakaan terbesar (luas dan koleksinya).
Suatu hal yang belum menjadi pilihan strategis bagi bangsa-bangsa yang mayoritas Muslim untuk dilakukan meski beberapa tahun yang lalu, Susan Mubarak (istri eks presiden Mesir Hosni Mubarak) mempunyai lembaga bernama Hai’ah al-Ammah lil-kutub, yang bertugas menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab dan membagi-jual dengan harga yang sangat murah. Kita umat Islam Indonesia juga telah melakukannya, tapi masih pada dataran individu dan sangat sporadis. Wallahu ‘alam. (Mukhlis Rahmanto)
—
Tulisan ini pernah dimuat di Majalah SM Edisi 19 Tahun 2017