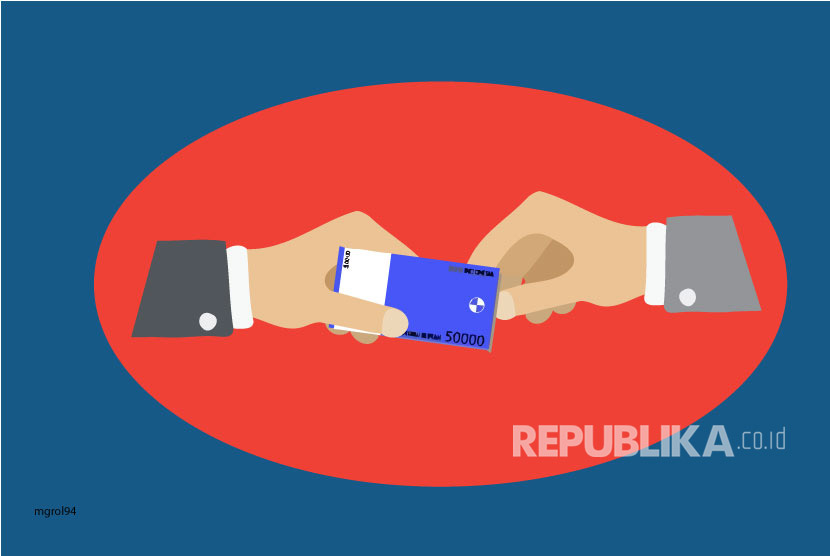REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merasa kesulitan mengantisipasi praktik politik uang dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu). Staf Ahli Bawaslu Bachtiar Faisal, saat diskusi di SETARA Institute mengakui itu. Namun menurutnya perlu konsistensi regulasi dalam penegakan politik uang. Yaitu dengan menyamakan subjek hukum dari praktik politik uang dalam setiap gelaran pesta demokrasi.
“Dalam (penegakan hukum) politik uang ada problem normatif yang menyulitkan,” kata Bachtiar di Jakarta, Jumat (5/4). Ia menerangkan, saat ini ada dua aturan yang berbeda terkait dengan politik uang.
Pertama dalam Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) 10/2016. Satu lagi pengaturan politik uang dalam UU Pemilihan Umum (Pemilu) 7/2017. Pada UU Pilkada, objek hukum dari politik uang adalah pemberi dan penerima. Dengan begitu, kata dia, praktik politik uang dapat dengan mudah dihindari lantaran pemberi dan penerima sama-sama dapat dihukum pidana.
Persoalannya, ada di UU Pemilu. Kata dia, dalam beleid tersebut, hanya pemberi yang terancam pidana. Kondisi tersebut, membuat penerima merasa tak bersalah menjadi bagian dari praktik politik uang. “Dalam rangka memperbaiki konstitusi, ini harus diubah.
Lebih bagus yang di UU Pilkada. Sementara kebutuhannya saat ini dalam Pemilu,” sambung dia. Pernyataan Bachtiar tersebut, sebetulnya menyoal tentang praktik politik uang yang menjadi sorotan menjelang Pilpres dan Pileg 2019. Baru-baru ini, Mabes Polri membeberkan catatan 31 kasus pidana politik uang selama kampanye terbuka.
Bachtiar mengatakan, menengok laporan Bawaslu sepanjang tahun Pemilu 2019, sebetulnya lebih dari empat ribu kasus terkait pelanggaran yang berpotensi pidana. Ribuan kasus tersebut lebih dari 31 kasus yang sebetulnya masuk dalam kategori politik uang. “Mengenai politik uang sebenarnya banyak sekali. Di setiap daerah pemilihan itu, ada,” ujar Bachtiar. Namun proses pemeriksaan di Sentra Penegakan Hukum (Gakkumdu) yang berisikan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan kerap tak sanggup menemukan syarat formal pidananya.
Sebab yang menjadi acuan tentunya UU 7/2017. Pada UU Pemilu, pembatasan pelaku politik uang pun terjadi. Yaitu hanya dikategorikan pada pemberi uang yang berasal dari tim kampanye, dan pelaksana kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kata Bachtiar, banyak laporan tentang politik uang yang sebetulnya dilakukan oleh mereka yang terdaftar di KPU, hanya praktiknya dilakukan oleh mereka yang tak tercatat di badan penyelenggara pemilu. Ia mencontohkan satu kasus di Tangerang Selatan (Tangsel) yang terang dilakukan politik uang, tetapi dilakukan oleh pihak lain agar masyarakat memilih seseorang.
Pada diskusi yang sama, Kepala Biro Operasional Bareskrim Polri, Irjen Nico Afinta menyampaikan politik uang mendominasi dugaan pelanggaran pidana Pemilu 2019. Sepanjang tahapan kampanye terbuka, terjadi 132 kasus dugaan pidana pemilu dari sebanyak 554 laporan. Sebanyak 31 di antara kasus tersebut merupakan dugaan pidana politik uang. Selebihnya kasus pidana pemilu terkait pemalsuan, atau manipulasi syarat kepesertaan pesta demokrasi, dan pelanggaran pidana lain.
“Kasus politik uang yang ada saat ini, masih konvensional. Artinya, ada calon yang memberikan uang cash (tunai) kepada pemilih,” ujar dia menambahkan. Nico mengakui politik uang dalam pemilu tahun ini tampak masif.
Apalagi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap pejawat calon legislatif dari Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso beberapa waktu lalu. Penangkapan anggota Komisi VI DPR RI tersebut, disertai dengan penyitaan alat bukti berupa uang kontan senilai Rp 8 miliar yang dipisah dalam 400 ribu amplop. Setiap amplop, berisikan lembaran uang antara Rp 20 atau Rp 50 ribu. KPK menduga, uang tersebut akan digunakan untuk politik uang. Yaitu dengan menyuap masyarakat pemilih saat hari pencoblosan, Pemilu 2019 pada 17 April mendatang.