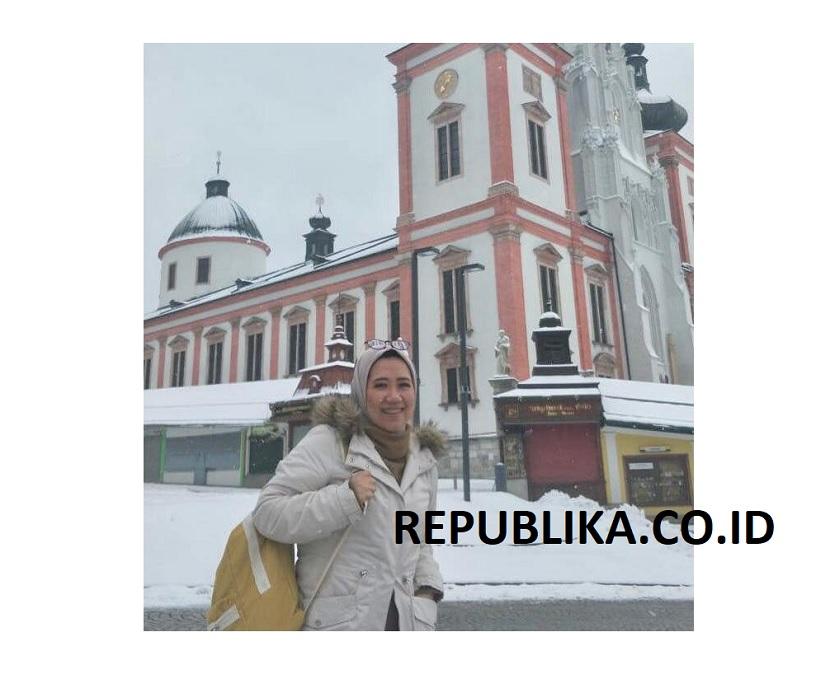“Dunia Baru" dan Nasib Demokrasi
Jean Baudrillard dalam Simulation (1983) merancang sebuah tesis yang memprediksi realitas pada akhirnya telah mati. Dunia baru yang Baudrillard sebut sebagai “galaksi simulacra”, ternyata melanda seluruh aspek kehidupan tidak terkecuali demokrasi.
Dialektika tentang demokrasi yang memberikan peluang bagi warga negara untuk bebas mengemukakan pendapat, justru berujung kebebasan yang menabrak batas-batas hak asasi manusia sesama warga bangsa. Diam-diam primordialisme diselundupkan melalui simbol-simbol agama, golongan, suku bangsa, kedaerahan, dan segala pengelompokkan sosial yang eksklusif. Kondisi itu justru menjadi belenggu baru yang membatasi kehidupan kebangsaan.
Kembali mengingat cita reformasi yang diperjuangkan pada 1998 yakni memperjuangkan kebebasan dari sistem tirani dan represi. Demokrasi seharusnya sudah lebih bersifat substansial ketimbang prosedural. Sayangnya, proses demokratisasi di Indonesia masih terbatas pada proses prosedural.
Celakanya, banyak aktor politik yang justru terjebak dan menjustifikasi proses prosedural ini. Prinsip-prinsip berdemokrasi, berpolitik, menyampaikan pendapat dan aspirasi, menjalankan pemerintahan dan lain sebagainya banyak mengabaikan prinsip-prinsip kebaikan dan kebenaran substansial. Semua itu dilakukan karena kepentingan pragmatis semata.
Lalu bagaimana nasib demokrasi? di ruang-ruang publik era postmodern, prinsip simulasi menjadi panglima sekaligus primadona. Pada konteks ini, reproduksi mesin politik menggunakan bantuan teknologi informasi, komunikasi. Membangun sebuah industri kuasa pengetahuan.
Opini para kaum intelektual bisa di pesan atau bahkan telah tersedia semacam menu khusus bagi para elite politik sebagai pemesan. Sementara pada saat bersamaan, permainan tanda dan citra mendominasi hampir di seluruh proses komunikasi kehidupan.
Pada sudut pandang masyarakat simulasi seperti ini, segala sesuatu ditentukan oleh relasi tanda, citra dan kode. Identitas seseorang capres-cawapres misalnya, tidak lagi ditentukan oleh dan dari dalam dirinya sendiri. Identitas tersebut bisa di-create sekaligus di rekonstruksi melalui gimmick, meski silang-sengkarut; tanda, citra dan kode tersebut tetap menjadi medan magnet yang digemari. Dengan kata lain, dalam dunia simulasi, bukan realitas yang menjadi cermin kenyataan, melainkan model-model yang ditawarkan televisi, iklan di medsos atau bahkan tokoh-tokoh fiksi yang kekorea-koreaan yang “kiyowo” “gemoy” dilengkapi rekaan melalui animasi dan kartun.
Pada akhirnya manusia mendiami suatu ruang realitas baru, tidak lagi berpijak pada prinsip demokrasi yang sarat nilai yang cita-citakan 24 tahun yang lalu. sehingga perbedaan antara yang nyata dan fantasi, yang asli dan yang palsu sangat tipis.
Manusia kini hidup dalam ruang khayali yang nyata, sebuah fiksi yang faktual. Melalui Twitter, TikTok, Instagram dan lainnya bahkan dalam media mainstream, dunia simulasi tampil secara sempurna. Narasi kebenaran peristiwa lampau seperti pelanggaran HAM berat, pengkhianatan terhadap konstitusi dan seluruh proses-proses hukum menjadi sumir. Menjelmalah ruang yang bernama “pesta demokrasi” yang abai dari nilai benar, salah, semuanya lebur menjadi satu dalam silang sengkarut tanda.
Mungkin ada benarnya nasib demokrasi itu tak lagi ditentukan ruang dan waktu. Waktu menjadi sesuatu yang nisbi. Ia bergerak tunduk pada titah pemilik kuasa.
Syahdan, ada waktu dari Nasib, waktu sebagai Kala, yang tak berubah dan tak mengubah. Demokrasi kehilangan arah, dalam Kala, manusia tak dapat lepas memilih dan memutuskan masa depannya dengan bebas. Manusia tak lagi menjadi subyek yang merdeka. Ia bisa menjadi heroik sekaligus culas.
Persoalannya adalah apakah demokrasi masih bisa diselamatkan? Apa yang akan terjadi setelah pemilu? mungkinkah subyek baru lahir, subyek yang melawan, yang merdeka, sebagaimana kisah Solon pada masa hidupnya. Ia berani melawan situasi di tempat ia hidup, merombak kondisi yang membentuknya, subjek yang terlepas dari posisi objek di bawah sang Kala, tak lagi tunduk pada simulacra belaka. Ia mampu membendung narasi keputusasaan wong cilik yang tereduksi dalam hastag #sayamuak.