REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif
Sebagai seorang yang tidak mengikuti persaingan keras dalam perusahaan elektronik global, terus terang saya terkaget-kaget membaca tulisan Yodhia Antariksa dalam majalah Nabil Forum (Jan-Juni 2013, hlm 21-22). Tulisan yang diberi judul “The Death of Samurai: Robohnya Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, dan Sanyo,” sungguh penting, menggelitik, dan kocak.
Siapa mengira, perusahaan elektronik raksasa Jepang yang telah merajai dunia selama lebih kurang 20 tahun kini nyaris tiarap, digempur telak oleh perusahaan Korea Samsung dan LG dengan kerugian triliunan rupiah. Maka, ungkapan “The Death of Samurai” (kematian samurai) dalam artikel Antariksa adalah simbol maut bagi dunia elektronik Jepang.
Dengan kata lain, pedang samurai kini sudah tumpul dan majal berhadapan dengan “pedang ginseng” Korea Selatan yang tajam. Korea dulu pernah dijajah Jepang, kini telah menaklukkan bekas penjajahnya itu di dunia elektronik.
Menurut Antariksa, setidaknya ada tiga penyebab utama mengapa Jepang kelimpungan berhadapan dengan Korea. Pertama, Jepang masih saja berpegang pada prinsip harmoni dan konsensus (Harmony Culture Error). “Di era digital seperti saat ini,” tulis Antariksa, “kecepatan adalah kunci. Speed in decision making. Speed in product development. Speed in product launch. [Cepat dalam mengambil keputusan. Cepat dalam pengembangan produk. Cepat dalam peluncuran produk]. Dan persis di titik vital ini, perusahaan Jepang termehek-mehek lantaran budaya mereka yang mengagungkan harmoni dan konsensus." (Hlm 21).
Ternyata di era yang serbadigital ini, peribahasa kuno "biar lambat asal selamat" harus cepat diganti dengan “cepat selamat". Antariksa dengan gaya kocak bercampur sinisme menulis, ”Datanglah ke perusahaan Jepang dan Anda pasti akan melihat kultur kerja yang sangat mementingkan konsensus. Top manajemen Jepang bisa rapat berminggu-minggu sekadar untuk menemukan konsensus mengenai produk apa yang akan diluncurkan. Dan, begitu rapat mereka selesai, Samsung atau LG sudah keluar dengan produk baru dan para senior manajer Jepang itu hanya bisa melongo.” (Hlm 21-22).
Kedua, masih bertahannya kultur yang mengutamakan senioritas (Seniority Error). Antariksa meneruskan, "Datanglah ke perusahaan Jepang dan hampir pasti Anda tidak akan menemukan Senior Managers dalam usia 30-an tahun ... Lalu apa artinya semua itu bagi inovasi? Kematian dini. Ya, dalam budaya senioritas dan loyalitas permanen, benih-benih inovasi akan mudah layu dan kemudian semaput. Masuk ICU lalu mati.” (Hlm 22).
Ketiga, faktor bangsa Jepang yang semakin menua (Old Nation Error). "Di sini berlaku hukum alam," tulis Antariksa. "Karyawan yang sudah menua dan bertahun-tahun bekerja pada lingkungan yang sama, biasanya kurang peka dengan perubahan yang berlangsung cepat. Ada comfort zone (zona nyaman) yang bersemayam dalam raga manajer-manajer senior dan tua itu.” (Hlm 22).
Itulah Jepang yang telah berjaya membangun bangsa dan negaranya dengan spektakuler dari puing-puing Perang Dunia (PD) II yang disudahi dengan bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat pada Agustus 1945. Sekarang, Jepang yang sama sedang dilumpuhkan pula oleh perusahaan elektronik Korea yang lebih inovatif, dan juga Cina, dengan harga yang lebih murah yang kini sedang membanjiri pangsa pasar global.
Jika Jepang saja kelimpungan, bagaimana kira-kira Indonesia dan dunia Islam yang lain? Tuan dan puan jawab sendiri! Kita sudah terlalu lama "menikmati" suasana sebagai umat konsumen, tunainovasi, dan tunasemangat kreatif. Untuk berapa lama lagi? Juga tuan dan puan yang bisa menjawab. Tetapi, harapan dan jeritan batin saya adalah, "Semoga Allah masih belum terlalu bosan dengan membiarkan kita tersungkur terlalu dalam untuk membangun peradaban yang adil dan nyaman di muka bumi.

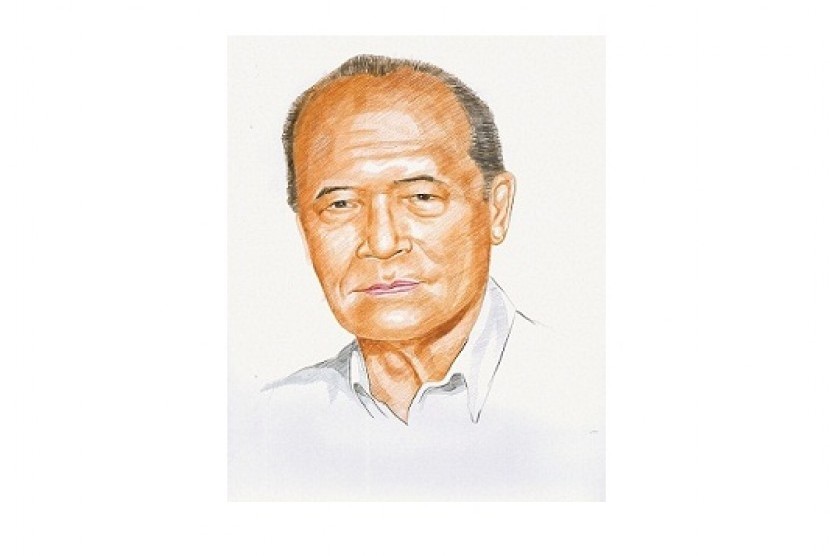

Komentar
Gunakan Google Gunakan Facebook