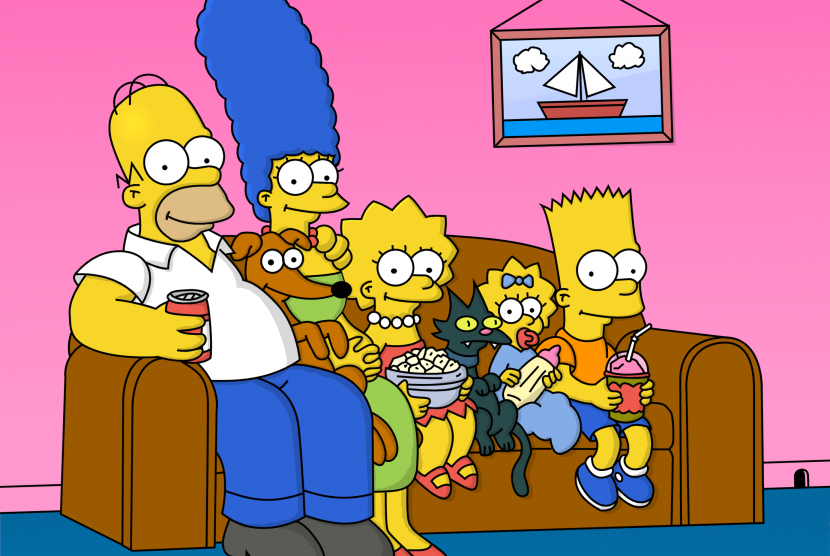REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Abdullah Sammy
Tahukah Anda, tiga senjata paling dahsyat milik Amerika Serikat yang bisa membuat Uni Soviet runtuh? Konon, tiga senjata itu jauh lebih dahsyat dibanding bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki.
Ketiga senjata paling mematikan milik Amerika itu adalah serial kartun The Simpson, Knight Rider, dan film Rambo.
Film, Rambo misalnya, menjadi propaganda Amerika di saat perang dinginnya melawan Uni Soviet era 1980-an. Film Rambo mampu memukul moral muda-mudi Soviet yang menyaksikan negaranya selalu dalam posisi antagonis. Di sisi lain, film yang dibintangi Sylvester Stallone tersebut menunjukkan betapa heroiknya prajurit Amerika.
Pun halnya serial Knight Rider yang mengisahkan seorang jagoan yang diperankan David Hasselhoff bersama mobil super canggihnya. Lagi-lagi di serial ini Soviet kerap ditampilkan dari sisi antagonis. Sisi lain dari film ini adalah bentuk propaganda mengenai kecanggihan teknologi milik Amerika yang digambarkan lewat mobil bernama Kitt.
Sedangkan serial kartun The Simpson garapan Matt Groening jadi salah satu tonggak penghancur Soviet. Sejak pertama kali diputar pada 1989 hingga awal 1990-an, the Simpson kerap menampilkan lelucon tentang Soviet.
Hal yang akhirnya membuat muda-mudi Soviet merasa malu akan negaranya. Serial itu pun lagi disebarkan Amerika ke wilayah Soviet, terutama ke wilayah perbatasan, yang masih bisa mengangkap sinyal antena dari negara lain.
Memang, Soviet sempat melawan serangan film Amerika itu dengan membuat tandingan Rambo, lewat film bertajuk Odinochnoye Plavanye garapan Mikhail Tumanishvili. Namun minimnya kualitas sinematografi membuat film itu tak mampu jadi tameng pelindung Soviet dari serangan Rambo, Knight Rider, dan The Simpson.
Pada akhirnya ketiga film Amerika itu sukses dengan propaganda politiknya. Muncul kemudian gerakan dari 12 Republik di Uni Soviet untuk memisahkan diri. Puncaknya Soviet bubar pada Desember 1991, atau dua tahun setelah serial The Simpson diputar perdana.
Apa yang terjadi di Soviet menggambarkan betapa kuatnya pengaruh budaya dalam mengangkat atau menghancurkan sebuah bangsa. Aktor Hollywood, Nicholas Cage pernah berucap, "Film bisa mengubah pemikiran seseorang. Dan itu adalah sesuatu yang sangat powerful."
Sejatinya memang tak hanya film yang bisa memengaruhi pola pikir. Segala industri kebudayaan populer pun jadi senjata yang bisa mengobrak-abrik alam pikiran hingga ke alam nyata. Sebagai contoh, tengok bagaimana musik rhythm and blues (R&B) bisa menjadi alat perjuangan masyarakat kulit hitam Amerika di era 1960 hingga 1990-an.
Awalnya, musik ini dipandang hanya sebagai musik etnis masyarakat Afro Amerika. R&B bersama turunannya seperti rap dan hip-hop lebih diidentikkan sebagai musik jalanan dan gengster.
Namun, lewat senimannya, seperti James Brown, musik ini mengalami metamorfosa. Brown memadukan kualitas vokal, gerakan, serta fashion yang membuat musik ini mulai dilirik. Perlahan tapi pasti R&B pun berkembang dari klub jalanan di permukiman Afro Amerika menuju gedung besar yang dipadati oleh berbagai etnis di Amerika, termasuk kulit putih.
Jadilah musik R&B bermetamorforsis dari budaya etik Afro Amerika menjadi budaya populer (pop) Amerika. Bersamaan dengan itu pula, eksistensi kaum kulit hitam Amerika mulai diterima secara politik.
Pada akhirnya lewat senjata budaya, dalam hal ini musik, kaum Afro Amerika bisa meruntuhkan segregasi di dalam masyarakat negeri Paman Sam. Salah satu tokoh yang berpengaruh dalam gerakan masyarakat Afro Amerika, Malcom X pernah berujar, "Budaya adalah senjata penting dalam perjuangan menuju kebebasan."
Amerika sudah menunjukkan bahwa kekuatan budaya mampu mengubah situasi di dunia. Bagaimana dengan di Indonesia? Sejatinya proklamator kita, Ir Sukarno sudah berpikir secara jangka panjang. Lewat konsep Trisakti-nya, Bung Karno sudah menegaskan betapa pentingnya Indonesia berdaulat secara kebudayaan.
Jauh sebelum keluarnya film Rambo, Sukarno pun sudah mewanti-wanti ancaman 'serangan' film barat yang disebutnya sebagai 'film dar der dor'. Pun halnya dari sisi musik yang mana muncul gerakan anti-'musik ngak ngek ngok'.
Tapi, gerakan itu nyatanya juga dimanfaatkan oleh kekuatan politik saat itu, yakni PKI lewat Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Muncul kemudian antitesis dari Lekra yakni Manifes Kebudayaan (Manikebu) yang menyatakan bahwa budaya tak boleh dikooptasi oleh politik, melainkan universal.
Pada akhirnya, budaya di Indonesia menjadi medan lain pertarungan politik antara para pemegang kekuasaan. Setelah PKI tumbang di tahun 1965, budaya, terutama film, memegang pernan cukup penting dalam membentuk prinsip dan ideologi bangsa.
Salah satu yang paling dikenang mungkin adalah film karya Arifin C Noer, Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. Film yang dibuat pada tahun 1984 dengan menghabiskan dana nyaris Rp 1 miliar itu bahkan jadi film yang wajib tonton sejak pertama kali diluncurkan hingga era reformasi 1998.
Di luar film tentang G 30 S PKI, Indonesia juga sempat punya film bernuansa nasionalisme, seperti Janur Kuning (1979), Serangan Fajar (1981), dan Tjoet Nja' Dhien (1988). Tapi lepas dari era itu, film Indonesia jadi berkubang dengan tema esek-esek, misteri, hingga cinta alay remaja di era kini.
Kini, era pemerintahan Jokowi seakan kembali ingin menghidupkan kembali cita-cita Bung Karno lewat ide Trisakti-nya. Salah satu ide Trisakti Bung Karno adalah berdaulat secara budaya.
Namun jika kita membuka layar kaca saat ini, istilah Trisakti ala Jokowi boleh jadi masih hanya sebatas lelucon saja. Televisi di Indonesia justru jadi cermin betapa majunya budaya Turki, India, maupun Korea. Kalaupun ada sinetron Indonesia, semua masih jauh dari kata mendidik, bahkan lebih tepat dikatakan merusak.
Memang di sisi lain, industri film Indonesia mulai bangkit. Tapi, sulit mengatakan bahwa film Indonesia saat ini sudah menjadi tuan rumah di bioskopnya sendiri. Sebaliknya, justru film asing semakin merajalela dengan sekuel-sekuelnya yang rutin menjamah setiap tahunnya.
Tak hanya film, dunia musik Indonesia saat ini sudah tak lagi jadi media yang menyuarakan perlawanan. Jika dahulu setiap jeritan rakyat mampu digubah menjadi lirik, kini beberapa musisi justru banyak menulis tentang sajak kampanye para penguasa. Musisi pun lebih sering terlihat di Istana.
Pada akhirnya perjuangan budaya yang sejati haruslah menjadi perjuangan dari 'jalanan' , bukan dari ruang Istana. Kebudayaan pun bukan doktrin dari isi kepala penguasa.
Di sisi inilah para pelaku budaya memegang peranan penting. Merekalah yang memegang peran untuk membuat film sebagai alat kemajuan atau justru alat kehancuran. Pun halnya mereka yang bisa menentukan apakah musik tetap menjadi suara 'jeritan', atau justru suara kekuasaan.