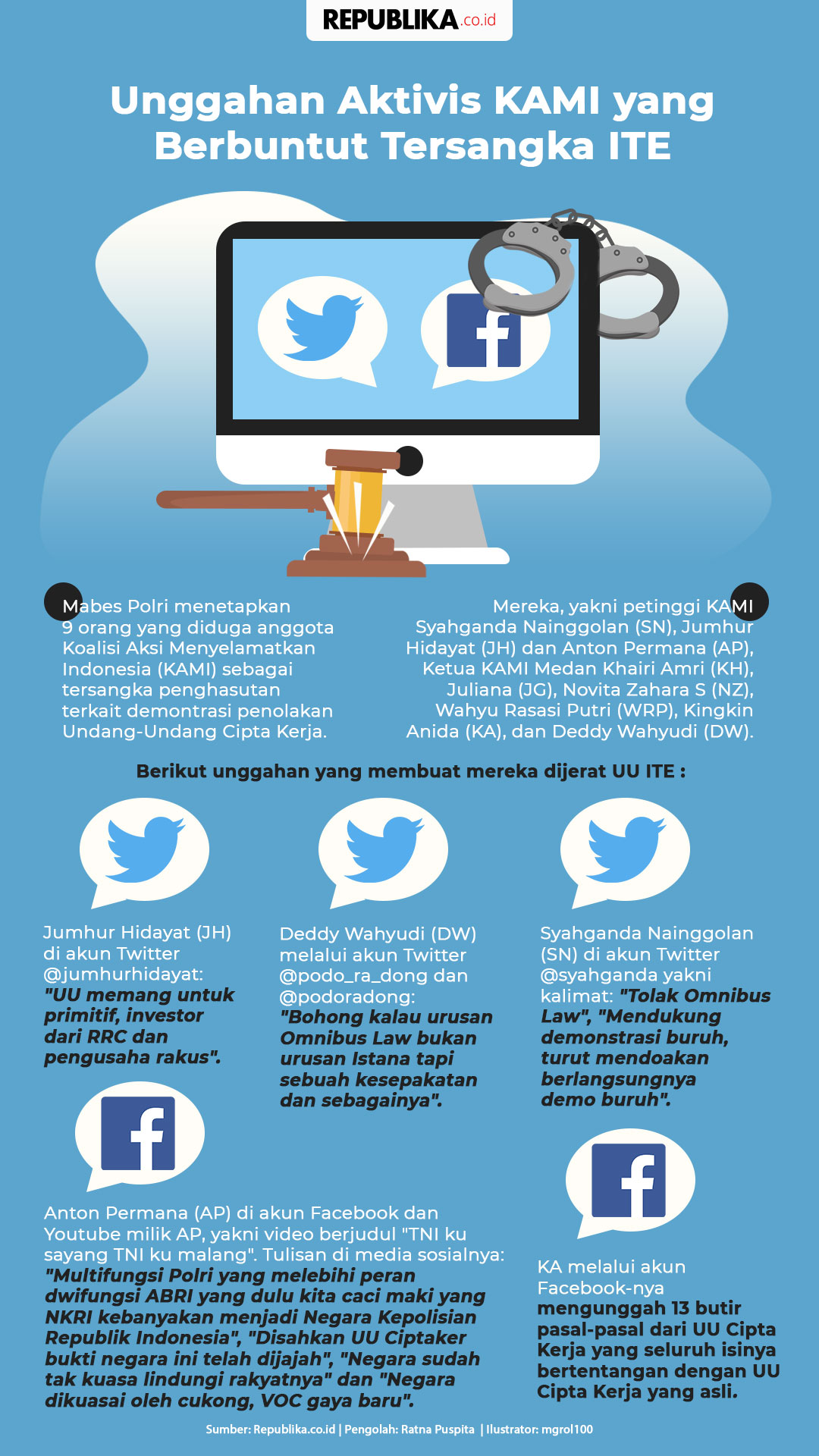REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Haura Hafizhah, Antara
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau UU ITE telah dicetuskan pemerintah. Pemerintah lalu diharap bisa berkomitmen karena selama ini kelompok pelapor terbesar yang menggunakan pasal-pasal dalam UU ITE adalah merupakan pejabat publik.
Manajer Program Lokataru Foundation, Mirza Fahmi, mengatakan bahwa revisi UU ITE membutuhkan komitmen dari pemerintah. "35,9 persen pelapor adalah kepala daerah, menteri, aparat keamanan, dan pejabat publik lainnya. Sedangkan pelapor dari masyarakat sendiri tercatat mencapai 32,2 persen," ujar Mirza dalam konferensi pers daring, Rabu (17/2).
Menurut data yang dihimpun SAFEnet pada 2019, setidaknya ada 3.100 kasus UU ITE yang dilaporkan. Sedangkan data dari Koalisi Masyarakat Sipil (ICJR) sejak 2016-2020, tingkat conviction rate pasal karet mencapai 96,8 persen atau 744 perkara.
Revisi pasal karet UU ITE, kata Mirza, dinilai tak akan banyak mengurangi kemampuan negara dalam mengkriminalisasi warga. Ini bukan hanya soal dokumen semata, tapi kemampuan pemerintah yang masih dipertanyakan saat berjumpa kritik," ujar Mirza.
Lokataru Foundation menemukan negara masih memiliki perangkat hukum lain yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Salah satu kasusnya adalah penggunaan pasal penghinaan terhadap mata uang Rupiah kepada Manre, nelayan Kodingareng yang merobek amplop berisi uang ganti rugi dari PT Boskalis.
Ditambah dengan penggunaan Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) yang kerap dipakai korporasi untuk memukul mundur perlawanan masyarakat. Di samping itu, ia menilai bahwa pemerintah memiliki "senjata andalan" untuk membungkan kritik, yakni kriminalisasi hoaks dan polisi siber.
"Melihat semua hal di atas, tanpa UU ITE pun kualitas demokrasi kita akan tetap mandek jika kita terus mundur. Pasal karet memang harus direvisi, namun kemunduran demokrasi di Indonesia tak bermula dan berakhir sampai sini saja," ujar Mirza.
Menurutnya, ada masalah yang mendasar pada turunnya indeks demokrasi di Indonesia. Tak hanya menyangkut pada pemerintah yang menyusun perangkat hukum, tetapi hal ini juga berasal dari dalam masyarakat.
"Ini juga mengendap dalam watak masyarakat sendiri, yang diam-diam menolak demokrasi yang menyarankan kebebasan berekspresi untuk semua," ujar Mirza.
Bukan hanya pemerintah yang bisa sepenuhnya bertanggung jawab atas kemunduran dalam kebebasan berekspresi tersebut. Mirza mengatakan pelapor warga dari elemen masyarakat pun banyak yang bersifat antikritik.
"Perbedaan tipis antara jumlah pelapor warga dan pemerintah membuktikan bahwa masyarakat sipil sendiri gagal memahami dan mempraktikkan kebebasan berekspresi. Tak ubahnya tabiat pemerintah," ujar Mirza.
Ia mengungkapkan, semangat memenjarakan lawan bicaranya juga ikut lestari terjadi di masyarakat. Masih banyak masyarakat sipil, kata Mirza, yang alergi terhadap kritik dan perbedaan pendapat.
"Tragisnya dibiarkan oleh pemerintah yang nampak meraup untung dari konflik warga yang berlomba-lomba mempolisikan sesamanya. Di momen politik besar seperti Pemilu atau Pilkada, kecenderungan ini melonjak berkali lipat," ujar Mirza.
Tak hanya merevisi, Lokataru mendorong upaya memulihkan korban kriminalisasi akibat undang-undang tersebut. "Untuk sesegera mungkin memulihkan korban-korban kriminalisasi pasal karet dari beleid yang ditandatangani 2011 silam. Hal ini untuk menunjukkan penyesalan atas praktik pemidanaan via UU ITE," ujar Mirza.
Ia melihat, UU ITE saat ini diamini sebagai salah satu sumber kemunduran demokrasi di Indonesia. Imbasnya, indeks demokrasi di Indonesia menurun sejak 14 tahun terakhir berdasarkan survei yang digelar oleh The Economist Intelligence Unit.
"Mungkin ini jadi momentum bagi Kapolri baru yang hendak berpegang pada prinsip restorative justice untuk memulihkan para korban," ujar Mirza.
Pasal karet yang ada dalam UU ITE memang perlu direvisi, tapi demi meningkatnya indeks demokrasi juga diperlukan komitmen dari pemerintah. Sebab tanpa undang-undang tersebut, negara tetap memiliki kemampuan dalam mengkriminalisasi warga.