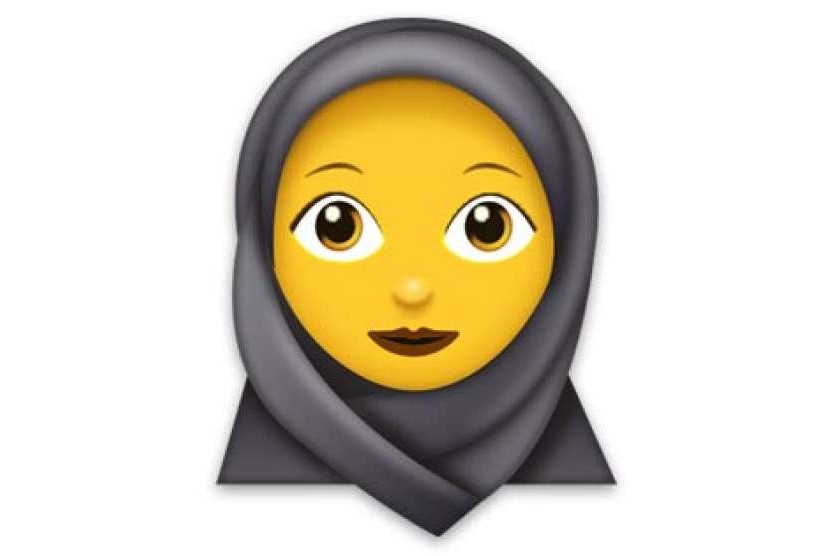REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Ratna Puspita*
Beberapa hari yang lalu, saya dan ibu saya berbicara soal harga-harga kebutuhan pokok di dapur. Ibu saya bilang, beberapa harga kebutuhan memang mengalami kenaikan.
Namun, ibu saya juga bilang, itu bukan sesuatu yang luar biasa. “Harga naik, ekonomi sulit, tetapi memang sejak kapan ekonomi enggak sulit,” kata ibu saya.
Ibu saya pun bercerita perekonomian mengalami perbaikan dalam beberapa hal, tetapi juga tidak bergerak dalam hal-hal lain. Misalnya, pemasukan bulanan yang lebih banyak dibandingkan beberapa tahun lalu sehingga membuat dia bisa mengalokasikan dana untuk kebutuhan-kebutuhan yang sebelumnya tidak terbeli.
Akan tetapi, ia menambahkan, kemampuan beli yang meningkatkan ini juga dibarengi dengan harga-harga sejumlah kebutuhan yang meningkat. Pada akhirnya, dia bilang, sama saja alias tidak ada perubahan.
Ia juga tidak bisa mengingat kapan ekonomi terasa lebih baik, termasuk pada masa Orde Baru. Saat itu, banyak harga murah, tetapi biaya sekolah saya dan dua saudara laki-laki saya menguras sebagian isi dompet. Sekarang, dua keponakan saya bisa sekolah gratis dan tidak pusing membayar biaya buku.
Ibu saya berbicara ini tidak terkait dengan politik. Dia tidak apolitis, tetapi juga tidak heboh urusan politik. Berbeda dengan ayah saya yang sangat getol terlibat dalam aktivitas politik.
Jika ayah saya kerap ‘mengampanyekan’ pilihan politiknya di dalam keluarga saya maka ibu saya sangat jarang mengekspresikannya. Dia bilang, “mama bilang milih apa juga kamu enggak tahu yang sebenarnya mama coblos di kotak suara.”
Mungkin seperti banyak anak lain di Indonesia, ibu saya adalah tempat belajar. Dia guru saya untuk urusan ekonomi, politik, dan berbagai hal lain. Dia adalah sekolah pertama saya untuk belajar nilai-nilai kehidupan.
Peran yang dilakukan ibu saya juga mungkin banyak dilakukan perempuan lain yang menjadi ibu rumah tangga. Ini kemudian mengingatkan saya dengan penelitian Kurt Lewin yang dipublikasikan pada 1943 berjudul Forces Behind Food Habits and Method of Change.
Saat itu, selama Perang Dunia II, Amerika Serikat mengirim daging ke luar negeri untuk makanan pasukannya sehingga harga daging di dalam negeri naik. Kala itu, pemerintah AS ingin masyarakat beralih ke daging organ dalam. Namun, banyak orang menganggap daging jenis ini sebagai makanan kelas rendah.
Lewin berusaha mengubah persepsi itu. Lewin menyatakan perempuan, bukan suami atau anak-anak mereka, mengontrol makanan mana yang muncul di meja Amerika. Perempuan atau ibu adalah penjaga gerbang (gatekeeper) yang mengendalikan makanan untuk keluarga.
Fungsi ibu sebagai gatekeeper ini kemudian diberlakukan dalam berbagai lini, termasuk media massa. Teori gatekeeping ini menekankan adanya peran krusial wartawan sebagai penjaga gerbang (gatekeepers).
Jika ibu menentukan makanan yang baik untuk disajikan kepada di atas meja makan maka wartawan memilih informasi yang baik untuk disajikan. Soal pilihan informasi ini, Bill Kovach dan Tom Rosentstiel menyatakan media massa harus meletakan loyalitas kepada masyarakat.
Kembali ke soal perempuan sebagai ibu rumah tangga. Politik memosisikan perempuan sebagai pasar yang harus diraih. Hal ini dilakukan baik oleh kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno maupun Joko Widodo.
Kubu Prabowo-Sandiaga mengeluarkan kampanye soal emak-emak yang identik dengan peran perempuan sebagai ibu. Slogan emak-emak ini menunjukan fokus kubu Prabowo-Sandiaga dalam persoalan ekonomi.
Seperti cerita tentang ibu saya di atas, emak-emak adalah orang pertama yang bersentuhan dengan persoalan ekonomi, yakni kenaikan harga. Sebab, ia bendahara keluarga. Emak harus bisa menyiasati antara pemasukan dan pengeluaran.
Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai tagline emak-emak ini merupakan opini tandingan dari klaim keberhasilan pemerintah di bidang ekonomi. Adi menilai kubu penantang ingin mengapitalisasi sentimen pemilih rasional yang berfokus pada kondisi ekonomi keluarga, di mana ibu atau emak-emak berperan sebagai pengatur keuangan.
Atas strategi kampanye ini, kubu Jokowi-Ma’ruf pun lagsung merespons. Kubu Jokowi-Ma'ruf memilih kata perempuan Indonesia. Perempuan lebih umum dibandingkan emak-emak.
Kubu Jokowi-Ma'ruf membentuk organisasi Perempuan Indonesia Jokowi-Ma’ruf Amin (IJMA). IJMA yang dipimpin oleh Ketua DPP PKB Ida Fauziyah ini akan fokus menggaet suara perempuan dalam ajang Pilpres 2019.
Ida, yang sempat berpasangan dengan Sudirman Said pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah 2018, menyatakan perempuan Indonesia tidak hanya terdiri dari kalangan emak-emak. Karena itu, model kampanye IJMA pun tidak hanya sebatas persoalan perekonomian. Sebab, perempuan memiliki kebutuhan beragam seperti tanggung jawab terhadap pendidikan keluarga, kesehatan keluarga, dan sebagai pengatur ekonomi keluarga.
‘Perang’ strategi emak-emak dan perempuan Indonesia ini pun sudah terlihat di media, baik media massa maupun media sosial. Kubu Prabowo-Sandiaga akan melontarkan pernyataan mengenai ekonomi, yang kemudian dibalas oleh kubu Jokowi-Ma’ruf.
Misalnya, dalam pernyataannya di media massa, Sandiaga kerap melontarkan pendapat tentang kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh perempuan. Pernyataan tersebut seperti Rp 100 ribu hanya cukup untuk beli bawang dan cabai, atau ukuran tempe yang setipis kartu ATM.
Kemudian, kubu Jokowi-Ma’ruf membuat video tentang barang belanjaan dengan budget Rp 100 ribu. Dengan anggaran tersebut, ibu bisa membeli berbagai macam bahan kebutuhan untuk dimasak.
Jika politik diibaratkan sebagai ‘perang’ maka strategi tersebut sah-sah saja. Akan tetapi, strategi semacam ini telah menempatkan perempuan sebagai pasar atau komoditas alias barang yang memiliki nilai tukar.
Pada posisi ini, isu perempuan hanya menjadi dagangan para politikus, yang didominasi oleh laki-laki. Karena hanya dagangan, perang emak-emak dan perempuan Indonesia ini tidak ubahnya ‘perang’ antarperempuan yang terjadi di masyarakat selama ini.
‘Perang-perang’ itu mulai dari perang ala Putri Salju dan ibu tirinya soal siapa yang lebih cantik hingga mana yang lebih baik antara susu formula dan air susu ibu. ‘Perang’ semacam ini justru terus membenturkan antarperempuan dan menjauhkan dari pemberdayaan perempuan.
Dalam hal politik, isu perempuan atau perbaikan kehidupan perempuan seringkali tidak mendapatkan dukungan politik. Bahkan, keterwakilan perempuan di politik hingga kini masih menjadi masalah.
Terkait hal ini, penelitian Ella S Prihantini (2018) menunjukkan masih ada kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Sebagian besar dari kedua jenis kelamin berpendapat bahwa hanya sedikit perempuan yang aktif terlibat dalam politik karena mereka memprioritaskan keluarga; suami dan anak-anak di atas karier politik.
Selain itu, sebanyak 20 persen legislator laki-laki yang menjadi responden dalam penelitian ini berpikir bahwa kuota 30 persen untuk perempuan tidak berdampak pada peluang perempuan menang pemilihan umum. Hal ini, misalnya, lantaran sangat sedikit perempuan yang dinominasikan sebagai kandidat nomor satu dalam daftar calon anggota legislatif. Persoalan lainnya bagi perempuan di politik, yakni kurangnya pelatihan politik serta modal sosial dan dana yang tidak mencukupi.
Karena itu, terpenting bukan ‘membenturkan’ perempuan pada persoalan harga kebutuhan untuk dimasak. Akan tetapi, rencana menjadikan perempuan subyek pembangunan yang sesungguhnya.
*) Penulis adalah redaktur Republika.co.id