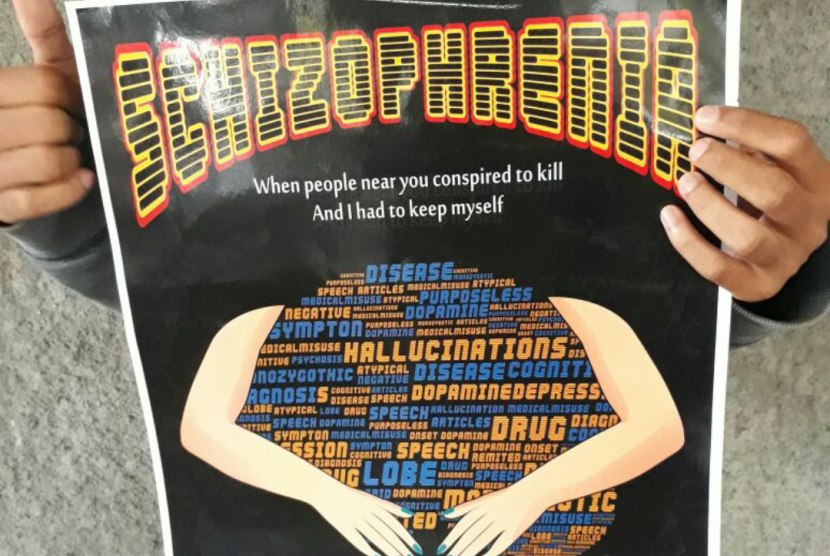REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Sri Handayani*
“Saya cukup prihatin. Meskipun lagu kebangsaan berkata bangunlah jiwanya, baru bangun badannya, tapi ternyata keberpihakan itu masih kurang. Kita masih hanya berpikir mati-hidup. Kematian ibu, kematian bayi. Kalau kita lihat indeks pembangunan kesehatan manusia, angka gangguan jiwa belum menjadi indikator. (Direktur RSJ Grhasia Etty Kumolowati)”
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah lama menjadi kota impian tempat tinggal sebagian masyarakat Indonesia. Nilai kultural yang tinggi didukung banyaknya sekolah dan kampus berkualitas di wilayah ini membuat DIY patut menyandang status kota budaya dan kota pendidikan selama puluhan tahun.
Kita boleh berharap dengan adanya kedua status tersebut, DIY mampu menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, terutama secara kultural dan akademis. Ironisnya, dua daerah istimewa di Indonesia, yaitu DIY dan Daerah Istimewa Aceh (DIA), justru menjadi kontributor tertinggi kasus gangguan jiwa berat di Indonesia.
Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan, DIY dan DIA memiliki prevalensi gangguan jiwa berat 2,7 per mil. Kulonprogo menempati kasus teratas dengan prevalensi 4.67, disusul Bantul 4.0, dan Kota Yogyakarta 2.14. Walaupun berada di posisi keempat, namun Gunungkidul disinyalir memiliki banyak kasus gangguan jiwa yang tak terungkap. Dari data yang ada dapat diperkirakan ada 2-3 penderita gangguan jiwa berat di antara 1.000 penduduk DIY. Total jumlah ODGJ di DIY diperkirakan mencapai 9.862 orang.
Gangguan jiwa berat merupakan masalah kesehatan yang serius. Butuh waktu lama untuk bisa pulih. Karena itu pula, jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) cenderung terus bertambah. Data rutin Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY pada 2015 telah menunjukkan angka sebesar 10.993 ODGJ. Di tahun 2016, jumlah itu menjadi 10.554 orang, belum termasuk Kabupaten Sleman.
Kepala Dinkes DIY Pembayun Setyaningastutie mengatakan tingginya kasus gangguan jiwa berat di DIY dan DIA tak lepas dari bencana alam besar yang pernah terjadi di kedua wilayah tersebut. Setelah terjadi gempa bumi pada 2010 di DIY, identifikasi dan pencatatan kasus-kasus potensi terjadinya gangguan jiwa dilakukan oleh pemerinah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sasaran utama merupakan korban bencana, khususnya di Bantul, serta masyarakat DIY secara umum.
“Hasilnya, penanganan secara dini dan recovery mental masyarakat DIY menjadi lebih cepat dan tepat,” kata Pembayun.
Jika menelisik lebih dalam lagi, gangguan jiwa berat juga dipengaruhi oleh gaya hidup dan beban hidup yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Menurut Pembayun, gaya hidup dapat menjelma menjadi tuntutan sosial yang pada akhirnya menjadi beban hidup bagi sebagian penduduk yang tak dapat memenuhi.
Sebagai contoh, telepon genggam menjadi kebutuhan bagi banyak orang. Di sisi lain, ini juga menjadi mode. Kepemilikan telepon genggam menuntut kebutuhan baru, baik untuk memenuhi kebutuhan pulsa, paket data, maupun pembelian unit baru agar tak ketinggalan zaman. Bagi yang tak dapat mengikuti, ini akan menjadi beban.
Kondisi ini didukung dengan aspek budaya masyarakat DIY yang terkenal santun. Tak elok menunjukkan beban kepada orang lain, sehingga banyak dari mereka memilih memendam bebannya sendiri. Bila tidak kuat, hal ini bisa menjadi potensi timbulnya stres dan depresi yang dapat berkembang menjadi gangguan jiwa berat.
Ironi lain muncul ketika kita melihat status DIY sebagai kota pelajar dengan kualitas pendidikan yang tinggi. Sayangnya, lahan pekerjaan di kota ini tak memadai untuk menampung lulusan sekolah dan perguruan tinggi yang kian tahun terus bertambah. Ini juga menjadi salah satu kontributor yang memicu stres atau gangguan jiwa.
Pendapat ini didukung oleh pernyataan Kepala Dinas Kesehatan (Dinsos) DIY Untung Sukaryadi. Ia mengatakan modernisasi mendadak yang menimbulkan keguncangan budaya (shock culture) memicu beban mental bagi sebagian masyarakat. Dengan tingkat intelektualitas yang belum siap, mereka akhirnya mengalami gangguan jiwa.
“Tekanan keluarga dan masyarakat itu turunannya. Tekannya malu, nggak kuat batin, sudah kehilangan muka,” kata dia.
Di Dinsos DIY, warga binaan lanjut usia (lansia) mendominasi jumlah gelandangan psikotik. Untung mengatakan keluarga perlu menyadari risiko gangguan jiwa pada lansia. Adanya post power syndrome merupakan hal wajar yang sering kali luput dari perhatian. Orang tua yang biasanya mampu memerintah anak-anaknya kini mulai kehilangan kekuasaan. Bahkan, sebagian dari mereka harus bergantung pada anak dan cucu. Ini menimbulkan beban psikologis bagi mereka.
Menurut Untung, tingginya kasus gangguan jiwa di Yogyakarta juga tak lepas dari kontribusi daerah-daerah sekitar. Jumlah gelandangan psikotik dari luar DIY mencapai 60-70 persen. Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Napza Baried Wibawa bahkan menyebutkan 80 persen.
“Tapi kan karena aspek kemanusiaan, kita tangani. Di kemudian hari cepat kita rujuk, kita pulangkan,” ujar Untung.
Menurut Untung, ada indikasi pengalihan tanggung jawab dari daerah-daerah di sekitar DIY. Beberapa indikasi yang dimaksud, di antaranya kemunculan ODGJ pada saat bersamaan di wilayah tertentu. Mereka ditemukan di daerah perbatasan, misalnya Jalan Magelang dan Jalan Godean. Walaupun sudah dilakukan razia rutin, keberadaan mereka seakan tak pernah habis.
Baried membenarkan keterangan ini. “Misal di Godean, kadang sudah bersih. Tapi tiba-tiba ada 2-4 orang ditemukan bersama-sama masih lengkap dengan kresek besar. Pernah juga ada yang melapor ke saya, ibu rumah tangga. Ada mobil boks yang mengeluarkan orang-orang ini,” kata Baried.
Padahal, menurut Baried, sejatinya dalam rapat mitra praja utama yang dihadiri para kepala dinas, telah ada 10 provinsi yang berkomitmen tidak saling melempar tanggung jawab dalam penanganan ODGJ. Kesepuluh provinsi itu adalah Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Keterangan ini juga didukung pengakuan Pendiri Pondok Pesantren (PP) al-Qodir, Cangkringan, Yogyakarta, KH Masrur Ahmad MZ. Ia mengaku pernah mengikuti mobil yang membawa ODGJ dan mendapati ada yang dilepaskan dari Solo ke Yogyakarta.
Menurut Masrur, pembuangan semacam ini berdampak buruk terhadap ODGJ. Pengalaman mereka dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain membuat mereka bingung. Belum lagi bermacam perlakuan yang mereka dapatkan selama dalam pembuangan. Ini memperparah kondisi mereka, sehingga semakin sulit disembuhkan. “Orang tidak sakit saja kalau misal tidur terus dilepas di daerah lain, kan bingung,” kata dia.
Peneliti Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Sri Idaiani mengakui adanya keterbatasan data untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengapa kasus gangguan jiwa berat di Indonesia tinggi. Sebab, tidak banyak hasil penelitian tentang gangguan jiwa. Selain membutuhkan waktu lama, penelitian di bidang ini memerlukan upaya yang intensif. Perlu waktu lebih lama untuk mendiagnosa gangguan kejiwaan yang dialami seseorang maupun penyebabnya. Upaya ini juga perlu memerlukan pendekatan yang sangat individual.
Akibatnya, sulit menjawab dengan pasti mengapa kasus gangguan jiwa berat di DIY paling tinggi. “Mungkin di sana memang paling tinggi, atau mungkin di sana ada banyak yang bisa mendeteksi, kesadaran yang lebih tinggi, sehingga ketika ada keluarga yang terindikasi gangguan jiwa langsung dilaporkan. Sehingga datanya banyak, padahal mereka itu ya yang aware,” kata Peneliti Kemenkes Sri Idaiani.
Selain itu, di tingkat kementerian, isu kesehatan jiwa juga belum lama menjadi prioritas. Dahulu titik berat penanganan kesehatan hanya mengacu pada Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) dan isu pertembakauan. Akhir-akhir ini kesehatan jiwa mulai mendapat perhatian karena telah masuk dalam standar pelayanan minimum (SPM). Pada 2014, Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa disahkan. Dalam Indikator Keluarga Sehat 2016 juga disebutkan bahwa ODGJ tidak boleh ditelantarkan.
Keberadaan regulasi ini menjadi motor penggerak bagi daerah-daerah di sekitarnya. “Dengan adanya program itu paling tidak dinkes di kabupaten/kota mempunyai dasar untuk mengajukan program dan anggaran. Karena kalau tidak ada SPM-nya, kita mengajukan program apa landasannya? Dengan SPM ini diharapkan bisa lebih berkembang,” kata Ida.
Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa dari Rumah Sakit (RS) Sardjito Ronny Tri Wirasta mengatakan secara umum ada dua kondisi gangguan jiwa, yaitu gangguan jiwa ringan dan berat. Gangguan jiwa berat secara sederhana dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang tidak dapat membedakan realita dan fantasi.
Gangguan ini juga bisa muncul ketika kehidupan seseorang terganggu, baik secara sosial, fungsional, maupun diri pribadi. Misalnya tidak mampu mengurus diri, gamang bersosialisasi, dan sebagainya. Gangguan ini juga dapat memunculkan ketidaknyamanan perasaan, misalnya marah tanpa sebab, mengamuk, dan sebagainya.
“Jenis gangguan jiwa berat bermacam-macam. Mulai yang paling berat skizofrenia. Ada pula psikotik akut, waham menetap, depresi berat dengan gejala psikotik, manic dengan gejala psikotik, bipolar dengan gejala afektif, banyak sekali,” kata Ronny.
Beberapa gejala dapat diamati secara kasat mata. Misalnya kegamangan merawat diri serta perbedaan perilaku yang mencolok. Gejala lain perlu dilihat melalui tes medis, misalnya untuk mengukur tingkat stres hingga gangguan organik atau fungsional.
Gangguan jiwa berat melibatkan tiga faktor penyebab, yaitu biologis, psikologis, dan sosial. faktor biologis, misalnya ketidakseimbangan neurotransmitter dalam otak. Faktor psikologis berkaitan dengan kepribadian pasien. Faktor sosial terkait dengan lingkungan sekitar, misalnya bullying di sekolah, masalah dalam pekerjaan, tuntutan sosial masyarakat, dan sebagainya.
Semua ODGJ berpeluang untuk sembuh. Namun, peluang itu terkait dengan tiga faktor penyebab yang telah disebutkan sebelumnya. Pengobatan juga perlu dilakukan dengan mempertimbangkan ketiga hal tersebut. Setiap ODGJ juga berpeluang untuk kambuh (relaps). Kasus ini dapat terjadi karena ketidakpatuhan minum obat maupun kehadiran faktor pemicu (stressor).
Gangguan jiwa berat berisiko menurunkan kemampuan kognisi, misalnya untuk berpikir, mengingat, mengambil keputusan, dan sebagainya. Gangguan kognisi akan berpengaruh pada kemampuan bekerja. Akhirnya, ODGJ menjadi tidak produktif. Selain itu, akan timbul rasa tidak nyaman. ODGJ dapat kehilangan kontrol terhadap perasaannya. Ia menjadi kerap berprasangka dan sedih atau senang berlebihan.
Kasus bunuh diri juga muncul pada ODGJ. Terkadang, ini terjadi tanpa disadari oleh pelaku. Sebagian ODGJ mungkin merasa mendengar perintah untuk bunuh diri. Ada juga yang merasa ada sesuatu yang masuk dalam dirinya dan memicu untuk bunuh diri.
Kasus ini tidak dapat diprediksi. Ada yang terjadi begitu saja, ada pula yang disertai tanda-tanda. Sebagian tanda yang perlu diwaspadai, misalnya ODGJ mulai menyendiri, mulai berbicara tentang kematian, tentang akhir hidup, keputusasaan, dan sebagainya. “Ada pula ODGJ yang membuat pesan tertulis tertentu,” kata Ronny.
Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Grhasia Etty Kumolowati menyebutkan ada peningkatan kasus gangguan jiwa berat cukup signifikan yang ditangani dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan tren yang semakin muda. Namun, ia tak menyebutkan detail penyebabnya.
“Saya khawatir, (trennya) semakin muda-e. Kelompok umur tetap di atas 30 (tahun). Kasus anak-anak kalau dihitung di bawah usia 18 tahun juga mulai muncul dengan kasus bipolar,” kata Etty.
Bagi dia, ini merupakan kasus serius yang suatu saat akan menjadi masalah besar. Gangguan jiwa berat umumnya muncul di usia produktif. Setelah menjadi ODGJ, sebagian besar kehilangan produktivitas.
“Satu gangguan jiwa berat, dia sangat jarang yang bisa mandiri secara ekonomi. Jadi kalau kita hitung potensial lost-nya, dengan 9.700 (ODGJ), kalikan saja dengan UMP,” kata dia.
Dengan upah minimum provinsi (UMP) 2017 sebesar Rp 1.337.645,25 dan data terbaru jumlah ODGJ 10.554 orang (tidak termasuk Sleman), selama sebulan, potensi kerugian yang dialami Pemerintah Provinsi DIY akibat ODGJ yang kehilangan produktivitas mencapai Rp 14.117.507.968,5. Dalam setahun, jumlah itu mencapai Rp 169.410.195.662. Ini belum termasuk pengobatan baik medis maupun non-medis.
Penelitian tentang besaran biaya medis dan non-medis untuk gangguan jiwa berat tipe skizofrenia pernah dilakukan tim Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (KPMAK) UGM. Dengan mengutip pernyataan profesor bidang kebijakan dan ekonomi, Martin Richard John Knapp, Peneliti KPMAK UGM Dyah Ayu Puspandari mengatakan skizofrenia merupakan penyakit kronis yang berkaitan signifikan dengan kondisi kesehatan, sosial, dan beban keuangan, tidak hanya untuk pasien, tetapi juga keluarga, caregiver, dan masyarakat luas. Hubungan antara kemiskinan dan skizofrenia menjadi saling timbal balik.
Tak hanya fasilitas kesehatan, pasien gangguan jiwa membutuhkan pembiayaan untuk rehabilitasi agar mereka mampu kembali menjalankan fungsi ekonomi. Bagi yang mampu kembali, biaya kambuh cukup tinggi. Skema pendanaan menjadi penting, terutama untuk membiayai pengobatan jangka panjang, perawatan ketika kambuh, rehabilitasi sosial, hingga mengobati masalah kesehatan lain.
“Sayangnya, yang bisa mengakses layanan ini masih kurang dari 10 persen. Anggaran biaya kesehatan kurang dari satu persen yang mengalir ke masalah kesehatan jiwa. Setelah ada jaminan pun, belum tentu keluarga memanfaatkan layanan ini,” ujar Dyah.
Ia menjelaskan, biaya dibagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. biaya langsung meliputi biaya langsung medis dan biaya langsung nonmedis. Biaya langsung medis terkait dengan rawat inap, rawat jalan, dan sebagian pengobatan efek samping serta pembelian obat. Ada pula biaya pengobatan komplementer dan pengobatan efek samping, serta pembelian obat di luar rumah sakit. Biaya langsung nonmedis meliputi biaya konsumsi, biaya transportasi, biaya terkait dengan perilaku kriminal pasien, biaya akomodasi, serta kerugian lainnya.
Biaya tidak langsung terdiri dari kehilangan produktivitas yang berkaitan dengan morbiditas dan mortalitas. “Pada penelitian ini parameter yang digunakan adalah meningkatnya pengangguran, penurunan produktivitas di tempat kerja akibat morbiditas, dan penurunan produktivitas caregiver akibat kehilangan waktu,” kata Dyah.
Adapun total biaya langsung medis untuk pasien gangguan jiwa di DIY mencapai Rp 9.504.548 per orang per tahun. Proporsi terbesar ada pada biaya rawat inap, yaitu Rp 5.718.767 (60,17 persen). Total biaya nonmedis mencapai Rp 5.254.550 dengan proporsi tertinggi pada biaya akomodasi sebesar Rp 1.618.075 (30,79 persen). Total biaya tidak langsung mencapai Rp 27.414.044, didominasi biaya akibat pengangguan Rp 22.765.150 (83,04 persen).
*Jurnalis Republika