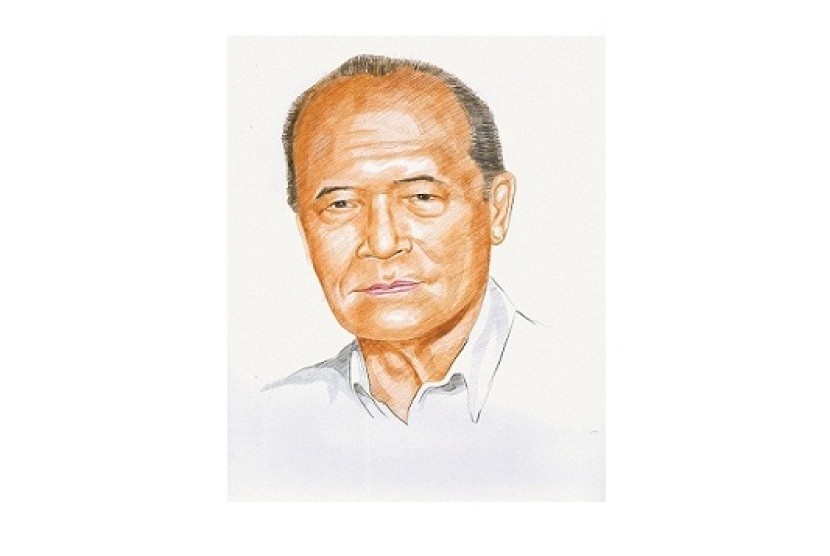REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif
Haji Hartoyo, pensiunan Pertamina, selesai shalat Jumat pada 8 Juni 2012 di masjid Nogo tirto, Sleman, bercerita tentang nasib seorang buruh tani dari Desa Biru, Kecamatan Gamping, Sleman, Yogyakarta. Sebut saja nama buruh tani itu Sutoyo (sekitar 50 tahun), penggarap sawah seluas 800 m2 di desa tetangga, Nusupan.
Sutoyo memerlukan tempo tiga bulan sampai hasil padinya bisa dipanen, kemudian langsung dibeli oleh tengkulak dengan harga yang dipatoknya sendiri sebesar Rp 900 ribu. Sutoyo tinggal pasrah saja. Dari harga penjualan ini, Sutoyo sebelumnya telah mengeluarkan biaya untuk beli benih, pupuk, dan ongkos traktor sebesar Rp 250 ribu. Yang tersisa hanya Rp 650 ribu.
Sisa inilah yang kemudian di bagi dua dengan pemilik sawah, masing-masing ke bagian Rp 325 ribu. Bila dalam bilangan bulan pendapatan Sutoyo—kalau panen berhasil baik—hanyalah Rp 108 ribu lebih sedikit. Tentu Sutoyo harus mencari kerja serabutan lainnya untuk menghidupi keluarganya sebagai buruh tani yang jumlahnya di seluruh Tanah Air sekitar 32 juta, melebihi penduduk Malaysia yang hanya 27 juta.
Jika Sutoyo bisa panen tiga kali setahun, angka Rp 325 ribu kalikan saja tiga, yaitu Rp 975 ribu, tidak sampai Rp 1 juta untuk sawah seluas 800 m2 itu. Inilah wajah buruh tani kita sejak zaman penjajahan yang hampir tidak mengalami perbaikan setelah 67 tahun kita merdeka.
Menyadari kenyataan buram ini, Presiden Soekarno telah mengeluarkan Keppres Nomor 169 Tahun 1963 yang menetapkan tanggal 24 September sebagai hari tani. Keppres ini tidak pernah dicabut, tetapi peringatan hari tani sudah tidak pernah dirayakan lagi. Keppres ini dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agra ria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 dengan tujuan agar petani mendapatkan keadilan. “Untuk menguasai sumber agraria, seperti tanah dan air kekayaan alam…”
Di bawah kekuasaan Orba, UUPA ini diabaikan begitu saja karena dianggap berbau komunis. Pada era reformasi dengan politik neoliberalismenya, pemerintah tampaknya juga cuek saja. Tidak ada kemauan memperbaiki kehidupan petani ini, apalagi buruh tani yang setiap hari terus menyabung nyawa demi melanjutkan pernapasan yang sudah lama terengah-engah, seperti yang dialami Sutoyo dan jutaan orang yang senasib dengannya di seluruh Indonesia.
Jadi, jika saya berkali-kali mengatakan bahwa sila kelima Pancasila telah menjadi yatim piatu sejak proklamasi tidaklah salah, bukan? Dengan kata lain, proses dehumanisasi nasib buruh tani malah semakin buruk dari tahun ke tahun. Apalagi sekarang, di Jawa khususnya, lahan pertanian sudah sangat menyusut, sebagian untuk perumahan, pasar, pabrik, dan bangunan-bangunan lain, yang berlangsung hampir tanpa kendali.
Jika tak salah ingat, Profesor Soemitro Djojohadikoesoemo pada abad yang lalu pernah menyalakan lampu merah, jika tidak hati-hati, Pulau Jawa pada suatu saat akan berubah menjadi padang pasir. Sebenarnya mereka yang prihatin atas kondisi buruk kehidupan buruh tani ini tidak pernah berhenti bersuara, tetapi suara itu tidak ada telinga yang bersedia mendengar.
Sebab, jika suara itu diperhatikan melalui politik negara yang propetani, posisi pengusaha- pengusaha besar yang mendapat untung bejibun manakala UUPA itu dilupakan saja akan goyang karena keadilan diberikan kepada petani untuk memiliki tanah, air, dan kekayaan alam yang lain di sekitar tanah itu. Dengan penguasaan tanah oleh pengusaha-pengusaha besar, kondisi petani pasti akan semakin buruk dan terpuruk sebab negara seakan-akan hanya diperuntukkan bagi para pengusaha besar dan golongan elite.
Oleh sebab itu, jika pemerintah yang sekarang tidak juga mempunyai kepekaan terhadap nasib petani ini, pemerintah yang akan datang wajib membela para petani ini, apalagi mereka yang tergolong buruh tani. Mereka tidak dibiarkan lagi melangsungkan hidupnya sebagai manusia yang tak berdaya, tak mempunyai masa depan.
Padahal, pada masa revolusi dulu, para petani inilah yang menghidupi para pejuang kemerdekaan tanpa meminta balas jasa. Karena sempitnya lapangan kerja di negara Pancasila ini maka para TKI kita yang sebagian berasal dari buruh tani tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus “berkeliaran” ke negara-negara lain dengan segala suka dukanya demi sesuap nasi.
Akankah Indonesia tercinta ini tetap membisu, tak mempunyai kepekaan untuk membela para petani kita? Saya sungguh berharap agar pemimpin yang akan datang mau membuka hati dan telinga untuk menjawab pertanyaan sentral ini sehingga rakyat sekelas Sutoyo yang jumlahnya puluhan juta itu merasakan apa makna ke merdekaan bangsa yang telah kita miliki selama lebih dari enam dasawarsa!