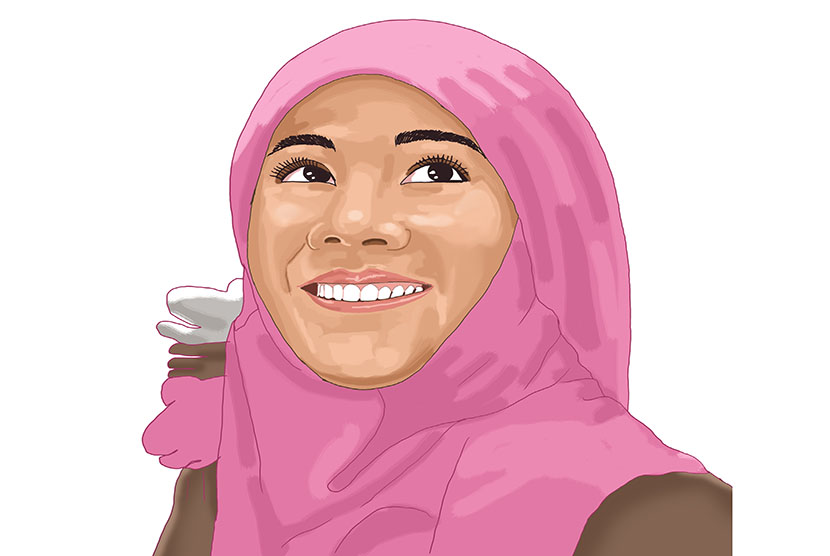REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Asma Nadia
Dalam sebuah tayangan video yang viral di media sosial (medsos), seorang pemuda berpeci dan bersarung dipaksa untuk membuka kardus yang dibawanya. Aparat dengan senjata laras panjang mengambil jarak dengan posisi siaga.
Sang pemuda membuka dengan susah payah kardus yang dibawa, kelihatannya sudah dilakban permanen sehingga tidak mudah. Dari bagian sempit yang dirobek, ia mulai mengeluarkan satu per satu isinya. Terlihat kesal, ia kemudian mulai membongkar dan melempar satu per satu pakaian dari dalam kardus.
Entah itu pakaian baru atau lama, bersih atau kotor, mungkin juga sebenarnya barang dagangan.
Belum usai kesal setelah mengobrak-abrik pakaian yang awalnya tersusun rapi, kini ia diperintahkan untuk membongkar pula isi ransel di punggung. Menahan perasaan, kembali sang pemuda mengeluarkan isi ransel. Beberapa waktu berlalu, tidak ada yang terjadi.
Tidak ada ledakan, tidak ada serangan atau hal membahayakan apa pun. Kecurigaan ternyata tak cukup beralasan.
Potret di atas merupakan kisi peristiwa. Semenjak aksi bom di Surabaya, aparat memang bersiaga mengantisipasi kemungkinan munculnya aksi lanjutan. Apalagi, pada hari berikutnya, kantor kepolisan menjadi sasaran serangan.
Di satu sisi, tentu siapa pun bisa mengerti langkah preventif yang dilakukan pihak keamanan. Upaya berhati-hati, tetapi di sisi lain, memprihatinkan sebab antisipasi keamanan masih terjebak pada stereotip fisik dan identifikasi.
Postingan video viral menyebutkan seorang "santri" digeledah. Ketika postingan itu tersebar, belum ada kejelasan siapa sebenarnya sang pemuda berpeci dan bersarung.
Benarkah ia santri? Tapi, medsos ramai sudah berasumsi demikian; sebab bersarung dan berpeci maka ia santri. Mungkin serupa apa yang ada di benak petugas keamanan saat itu.
Secara tidak sadar, sekalipun berdasarkan pengalaman sementara, seolah bahwa teroris adalah Muslim. Lalu mulai ter-frame sosok Muslim yang berjenggot, wanitanya berjilbab dan bercadar, serta mulai terekam identifikasi fisik lainnya. Dengan pola ini, terjadilah apa yang menimpa sang santri.
Belakangan dari berita terungkap bahwa setelah semuanya aman, sang pemuda yang terkonfirmasi memang seorang santri dan polisi, saling memaafkan. Keduanya bahkan sempat berswafoto bersama. Tidak ada dendam, tidak perlu dibesar-besarkan.
Salah satu ending yang membahagiakan. Persoalannya mampukah pengujung adegan video viral tadi benar-benar menjadi akhir yang menyejukkan? Akhir yang terjejak kuat dalam benak semua pihak.
Lihatlah kelapangan hati sang santri. Setelah diperlakukan tidak menyenangkan, setelah dituduh tanpa alasan, setelah tersita waktu dan tenaga, juga terkikis harga diri, dengan mudah ia malah memaafkan. Sempat-sempatnya bersuka cita tanpa dendam.
Inilah sikap yang insya Allah mewakili wajah umat Islam kebanyakan sebagaimana yang berusaha disyiarkan lewat film 212 The Power of Love yang sedang tayang di bioskop. Islam itu peace and love. Sebagian besar umat Islam Indonesia adalah pemaaf.
Sebagian besar umat Islam Indonesia sangat toleran. Nyaris semua cinta damai. Garis bawahi hal ini.
Jangan kemudian karena perilaku satu atau dua orang yang kebetulan beragama Islam, yang kebetulan memahami agama secara salah, yang kebetulan tidak paham ajaran Islam yang penuh damai, seluruh umat Islam lantas menjadi korbannya.
Memandang terorisme dengan kacamata stereotip sangat berbahaya, kita bisa dengan mudah teperdaya.
Padahal, pembunuh delapan orang di Oslo lalu pembantai 77 orang remaja di Pulau Utoya, Anders Behring Breivik, tidak mengenakan sarung atau kopiah. Pun tidak berjenggot. Jelas bukan seorang Muslim.
Sosok yang menghabisi nyawa 58 jiwa dan melukai 851 orang di sebuah konser di Las Vegas, Stephen Paddock, juga tidak mengenakan serban atau peci. Dia bahkan bukan dari kalangan miskin yang tidak punya penghidupan.
Ia meluncurkan serentetan tembakan dari satu kamar di sebuah hotel mewah.
Di Swedia kini juga gempar dengan munculnya aksi kekerasan (baca: teror) yang membuat takut warga yang dilakukan seseorang berpakaian badut.
Semua fakta ini menunjukkan bahwa melabelkan kelompok tertentu (baca: Muslim) dengan pakaian dan tampilan fisik khas (baca: berjilbab, bercadar, celana cingkrang, berjenggot) justru akan mengekalkan dua keburukan.
Pertama, jelas menyakiti umat yang sama sekali tidak terlibat terorisme bahkan juga membencinya.
Kedua, bisa-bisa kita akan ditembus oleh aksi teroris yang tampil dengan tampilan fisik berbeda. Jika seorang Anders datang dengan jas, kita tidak akan menduga, juga seperti kejadian di Swedia saat sosok teroris datang justru dengan baju badut.
Baru-baru ini sebuah pemandangan menyejukkan terlukis di rumah sakit, ketika Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengunjungi seorang polisi yang menjadi korban serangan aksi teror, ternyata istrinya mengenakan cadar.
Tentu saja ini menyejukkan. Pertama, karena kepolisian tidak mempermasalahkan anggota polisi mempunyai istri bercadar. Kedua, menunjukkan bahwa teroris adalah musuh semua. Teroris tidak punya mata dan hati.
Teroris sejatinya musuh wanita bercadar, musuh para Muslim yang memelihara janggut, pun musuh lelaki bercelana cingkrang, atau beserban, mereka pun musuh lelaki bersarung.
Teroris adalah musuh umat Islam, musuh umat beragama, musuh Indonesia. Lawan bersama!
Baca Juga: Jokowi: Ideologi Teroris Telah Masuk ke Dalam Sendi Keluarga