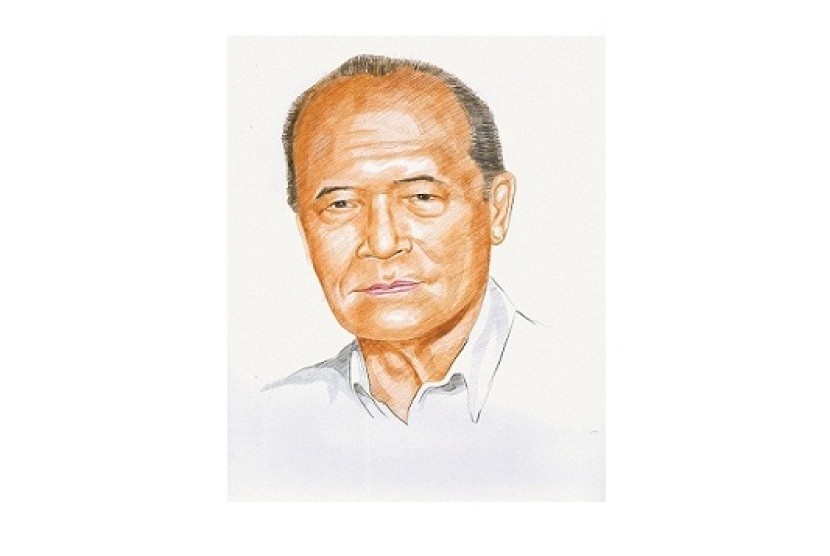REPUBLIKA.CO.ID, Demikianlah, misalnya, Perang Aceh yang berlangsung selama 40 tahun itu akhirnya terempas. Kualitas persenjataan Aceh sama sekali tidak lagi memadai untuk meneruskan perlawanan.
Akibatnya sangat logis, semangat yang semula demikian tinggi melawan orang kaphe (kafir) akhirnya redup juga dengan segala penderitaan dan kehinaan yang diwariskannya. Inilah kesaksian T Ibrahim Alfian, sejarawan Indonesia asal Aceh. “Setelah empat puluh tahun berperang, para pemimpin agama yang masih tinggal, pada umumnya sudah tidak mempunyai cukup potensi lagi untuk menghadapi persenjataan Belanda. Pemimpin-pemimpin agama ada yang duduk sebagai kali atau hakim agama dalam pemerintahan uleebalang yang mengakui kedaulatan Belanda mereka, termasuk dalam struktur birokrasi pemerintah kolonial Belanda.” (T Ibrahim Alfian, Perang di Jalan Allah. Jakarta: Sinar Harapan, 1987, hlm 236).
Aceh adalah daerah modal yang tersingkat dijajah Belanda, hanya berlangsung 30 tahun (1912-1942). Rakyat Aceh boleh berbangga dengan fakta ini. Kekalahan Aceh ini tidak berarti bahwa rakyat nusantara menyerah kalah, tetapi strategi perlawanan berubah: dari modal fisik dan iman ke modal intelektual melalui organisasi modern. Lahirnya BU (Budi Utomo) 1908, kemudian SI dan Muhammadiyah yang muncul bersamaan dengan kekalahan Aceh ini adalah pertanda penting dari titik geser strategi perjuangan itu.
Namun, gerakan intelektual yang didukung oleh semangat nasionalisme dan gagasan demokrasi baru terjadi pada 1920-an, dipelopori oleh mahasiswa yang terhimpun dalam Perhimpunan Indonesia (PI) di negeri Belanda dan di dalam negeri disambut oleh gerakan pemuda Indonesia yang kemudian berikrar dalam bentuk Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang terkenal itu.
Para intelektual ini sekaligus adalah aktivis politik kebangsaan, sesuatu yang logis di tanah jajahan. Berkat pendidikan Barat, mereka ini menjadi sangat sadar tentang betapa hina dan nistanya hidup di bawah sistem penjajahan. Islam yang menghargai martabat manusia merdeka merupakan salah satu faktor pemicu utama untuk menghalau penjajahan dari bumi nusantara.
Dalam rahim 1920-an ini pulalah, munculnya Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1923 dan organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) yang resmi berdiri pada 31 Januari 1926. Pada 4 Juli 1927, lahir pula Partai Nasional Indonesia (PNI) pimpinan Ir Sukarno yang pada era kemerdekaan menjadi presiden pertama Republik Indonesia.
Jika NU lebih banyak bergerak di dunia pesantren dengan peran para kiainya yang fenomenal, PNI adalah partai kaum intelektual didikan Barat, persis dengan PI yang seluruhnya dibidani oleh kaum terpelajar didikan Eropa. Dalam gagasan nasionalisme dan demokrasi modern, kelas intelektual yang dihasilkan oleh Muhammadiyah dan NU pada umumnya belum bisa menandingi kualitas kelompok intelektual didikan Barat. Mungkin inilah salah satu penyebab mengapa dalam proses perjuangan kemerdekaan kaum santri yang diwakili Muhammadiyah dan NU lebih banyak berfungsi sebagai pendamping mitranya yang mendapatkan pendidikan Barat.
Dalam PI, misalnya, kecuali Dr Soekiman Wirjosendjojo yang kemudian dapat dikategorikan sebagai wakil kaum santri, yang lain adalah kelompok intelektual nasionalis yang tidak menjadikan agama sebagai filsafat perjuangannya sekalipun mayoritas mereka adalah penganut agama Islam. Tokoh PI, Mohammad Hatta, sekalipun dikenal sangat saleh dalam hidup beragama, ideologi yang mendasari perjuangan politiknya adalah nasionalisme, tidak berbeda dengan Sukarno.
Memang pada 1967 Hatta, Deliar Noer, dan banyak dari alumni HMI berniat mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII), tetapi sayang partai ini bernasib abortif karena tidak diizinkan rezim militer Soeharto untuk dilegalkan dengan dalih penyederhanaan sistem kepartaian. Bung Hatta, seorang demokrat dalam teori dan praktik, tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali mengurungkan niat mulianya itu.
Sewaktu bertemu dengan Deliar Noer di kampus Universitas Chicago pada 1980, Nurcholish Madjid (1939-2005) menurunkan refleksinya berikut ini tentang PDII. “Kalau sekiranya Partai Demokrasi Islam Indonesia yang dipimpin Hatta jadi berdiri, keadaan di Tanah Air agaknya tidak separah yang kita hadapi.”
Seperti kita ketahui, Bung Hatta adalah idola Nurcholish Madjid dalam masalah kenegaraan dan demokrasi. Rezim militer tentu sangat sadar, sekiranya PDII sebagai pembela sistem demokrasi yang sehat diizinkan berdiri, tentara tidak mungkin berbuat 'semau gue' dalam mengebiri demokrasi atas nama demokrasi Pancasila.