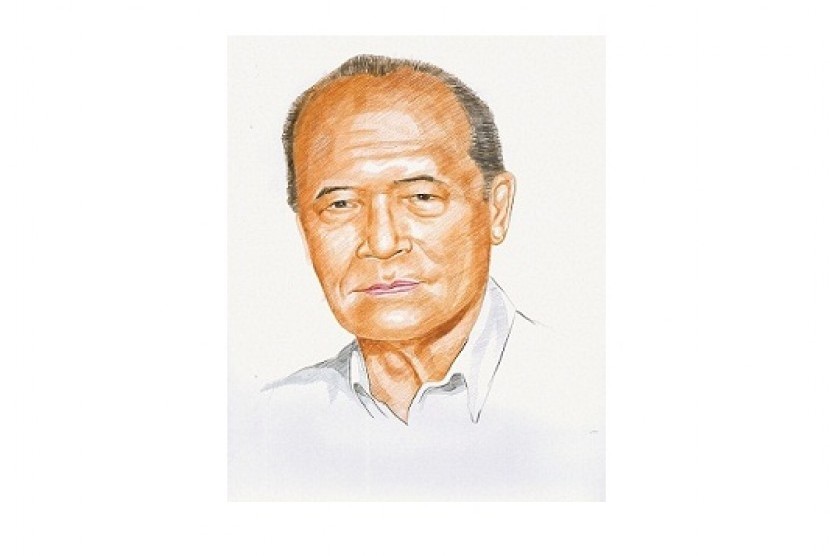REPUBLIKA.CO.ID,Oleh: Ahmad Syafii Maarif
Pidato Pembelaan Bung Hatta di depan Mahkamah Belanda di Den Haag, pada bulan Maret 1928 di bawah judul “Indonesie Vrij” (Indonesia Merdeka) dan Pidato Pembelaan Bung Karno di depan Pengadilan Kolonial di Bandung, bulan Agustus 1930, dengan judul “Indonesia Menggugat” terasa masih relevan dengan situasi Indonesia sekarang ini.
Relevansi itu semakin terasa bila dikaitkan dengan masalah kedaulatan kita di bidang ekonomi yang semakin didikte oleh pihak asing, terutama sejak krisis moneter di akhir abad yang lalu. Ketergantungan Indonesia pada “instruksi” IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia dalam mengatasi krisis melalui BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) sebesar Rp 650 triliun telah semakin menyengsarakan sebagian besar rakyat Indonesia, demi penalangan negara terhadap 'pengusaha hiu' yang sedang kelimpungan saat itu.
Bung Hatta dalam kritik kerasnya kepada sistem kolonialisme dan imperialisme mengutip pendirian PI (Perhimpunan Indonesia) di negeri Belanda melalui ungkapan ini: “Lebih suka kami melihat Indonesia tenggelam ke dasar lautan, daripada melihatnya sebagai embel-embel abadi daripada suatu negara asing.” (Lihat hlm. 136-137).
Ungkapan sangat berani ini adalah inti pesan kemerdekaan bangsa yang paling autentik yang dialamatkan kepada Belanda yang tidak punya niat untuk mengendorkan nafsu kolonialnya atas tanah jajahannya. Bung Hatta ketika menyampaikan pidato itu baru berusia 26 tahun, tetapi api patriotisme dan nasionalismenya siap menghadapi segala risiko dari pernyataannya itu. Tidak hanya sampai di situ, Bung Hatta menantang lebih lanjut: “Jika tiba saatnya maka Nederland (Belanda, red) akan ditempatkan pada alternatif, mengundurkan diri dengan sukarela dari Indonesia atau dilemparkan ke luar dari Indonesia.” (Hlm. 139). Siapa yang tidak merinding bangga dengan sikap patriot sejati pada sosok Hatta ini.
Bung Karno dengan sangat jeli telah melihat kemungkinan bahwa imperialisme bisa mengalami metamorfose (perubahan bentuk, tetapi hakikatnya sami mawon (sama saja, red)). Kita kutip: “…imperialisme bukan saja sistem atau nafsu menaklukkan negeri dan bangsa lain, tapi imperialisme bisa juga hanya nafsu atau sistem memengaruhi ekonomi negeri dan bangsa lain. Ia tidak usah dijalankan dengan pedang atau bedil atau meriam atau kapal perang, tak usah berupa ‘perluasan negeri (sic.) daerah dengan kekuasaan senjata’ sebagai yang diartikan oleh van Kol, tetapi ia bisa juga berjalan dengan ‘putar lidah’ atau cara halus-halusan’ saja, bisa juga berjalan dengan cara penetration pacifique [penetrasi damai].” (Hlm. 17-18).
Siapa yang bisa menafikan bahwa Indonesia sekarang sedang berada dalam perangkap “halus-halusan” pihak neo-imperialisme yang telah merampas kedaulatan kita di bidang ekonomi dari tangan kekuasaan para elite dengan mentalitas terjajah. Quo vadis Indonesia?
Agar kondisi terjajah Indonesia di bidang ekonomi tidak dibiarkan lebih berlarut-larut lagi, saya sarankan dengan sangat agar pemimpin Indonesia yang akan datang bersedia menelaah kembali dua pidato Bung Hatta dan Bung Karno di atas. Tanpa berdaulat penuh di bidang ekonomi, kemerdekaan bangsa bisa menjadi sebuah ilusi, dan itu sangat menyakitkan batin semua patriot yang masih tersisa. Tren neo-liberialisme dengan ideologi ekonomi pasar yang masih dipertahankan sampai detik ini bagi saya adalah sebuah pengkhianatan telanjang terhadap seluruh cita-cita suci kemerdekaan bangsa.
Ruh Bung Hatta dan ruh Bung Karno di alam sana pasti merintih dan menjerit karena menyaksikan Indonesia sejak 40 tahun terakhir telah tergadaikan, sementara pihak penguasa tidak merasa berdosa dan tetap senyum-senyum saja. Senyum manusia inlander