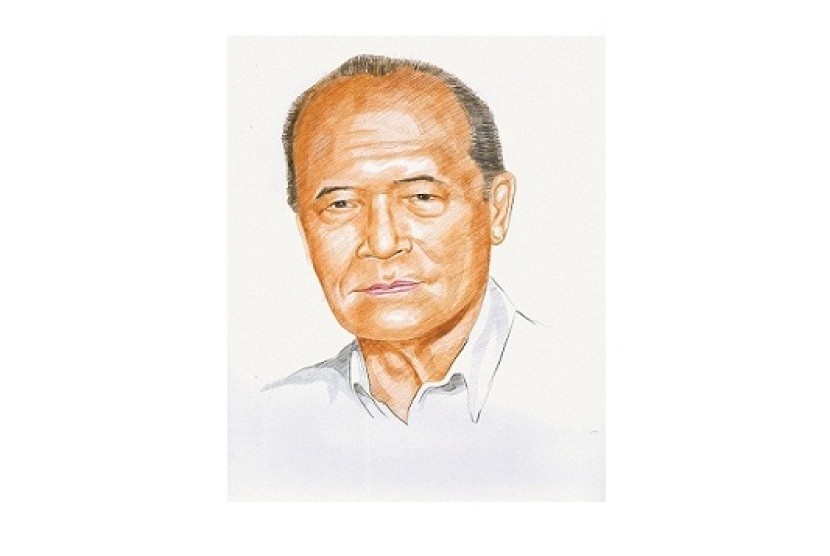REPUBLIKA.CO.ID,oleh: Ahmad Syafii Maarif
Dalam bacaan saya, jawabannya terkait dengan politik luar negeri Amerika yang jingoistik (cinta tanah air yang berlebihan) dan ekspansif. Akibatnya, pada era Presiden Bush terutama, selalu merasa terancam oleh kekuatan luar yang membahayakan negaranya, sesuatu yang sama sekali palsu. George Bush adalah seorang paranoid (hidup dalam ketakutan).
Suasana batin yang labil ini dimanfaatkan secara maksimal oleh gerakan Zionisme, demi eksistensi Israel yang sebenarnya tidak lain ialah sebuah negara teror. Berbeda dengan Todd dan Galtung yang anti-Zionisme, Fukuyama sendiri tampaknya tidak punya nyali yang cukup untuk berbicara terus terang tentang ideologis fasis ini.
Todd sekalipun menghindari menyebut Zionisme, tetapi melihat dengan jelas peran strategisnya dalam mencoraki politik Amerika, dalam dan luar negeri. Todd juga punya perasaan simpati atas nasib rakyat Palestina dalam cengkeraman kolonisasi Yahudi. Kita baca, “Ketidakadilan terhadap rakyat Palestina dari hari ke hari oleh kolonisasi Yahudi atas sisa-sisa tanah mereka dengan sendirinya adalah sebuah penyangkalan terhadap prinsip persamaan, yang menjadi fondasi demokrasi. Bangsa-bangsa demokrasi lain, terutama di Eropa, tidak punya simpati tanpa syarat terhadap Israel seperti yang dirasakan Amerika.” (Todd, hlm 114).
Adalah sebuah keheranan besar, penduduk Yahudi Amerika hanyalah sekitar 2.2 persen (Todd, hlm 115) dari total rakyat Amerika, mengapa perannya demikian menentukan? Dengan runtuhnya imperium Amerika, jawaban terhadap pertanyaan ini akan lebih mudah diperkirakan. Artinya, peta politik global akan berubah secara drastis, dan nasib Israel akan jadi taruhan, karena pelindung utamanya telah menarik diri sebagai sebuah imperium.
Dan, tidak tertutup kemungkinan Palestina akan muncul sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat. Jika ini terjadi, terorisme akan surut secara dramatis dan tiba-tiba, karena raison d'trê (pembenaran eksistensi) utamanya sudah tidak ada lagi. Perasaan aman secara global akan mengikutinya sebab biang kerok kekacauan ini tidak lain dari politik luar negeri Amerika yang paranoid di bawah pengaruh kuat Zionisme, yang memang “bukan bagian dari kemanusiaan”, tulis Gilad Atzmon (lihat Resonansi, 13 Januari 2009 dan 10 Juni 2010). Bagi Galtung, untuk mengakhiri terorisme, akhiri lebih dulu terorisme negara, maksudnya Amerika dan Israel. (Telusuri artikel Galtung dan Dietrich Fischer via Google, 20 September 2002, di bawah judul “To End Terrorism, End State Terrorism”).
Fukuyama yang semula adalah bagian kekuatan neo-konservatif berubah 180 derajat setelah Presiden George Bush menyerang Iraq dan menggantung Saddam Hussein. Maka beberapa tahun kemudian, muncullah buku keduanya di bawah judul "America at the Crossroads: Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy" (New Haven-London: Yale University Press, 2006) sebagai ralat terhadap optimismenya yang berlebihan tentang hari depan kapitalisme dan demokrasi liberal.
Jika buku ini ditulis setelah krisis keuangan Amerika tahun 2008, tentu analisis Fukuyama akan lebih tajam lagi. Ternyata kapitalisme dengan doktrin pasar bebasnya punya penyakit kronisnya tersendiri, sesuatu yang tak terbayangkan sebelumnya oleh seorang Milton Friedman (31 Juli 1912-16 Nop. 2006), ekonom pro-pasar, pemenang Hadiah Nobel Ilmu Ekonomi tahun 1976, yang pernah dipuja dunia itu, termasuk oleh pengikutnya di Indonesia.
Karya Fukuyama ini masih perlu kita bicarakan lagi, terutama yang menyangkut isu jihad yang kemudian semakin menyebabkan Presiden George Bush jadi gelap mata untuk menyerang negara-negara yang dikatakan sebagai pusat terorisme dan senjata kimia pemusnah massal, semula Afghanistan kemudian Iraq. Akibat serangan imperialistik itu, dua bangsa Muslim ini berantakan dengan korban jiwa ratusan ribu. Tetapi, akibatnya bagi Amerika tidak kurang fatalnya: mempercepat proses kerontokan imperiumnya yang baru saja mencapai titik puncaknya pada 1991 (Zakaria, hlm 4).
Jika ramalan Galtung menjadi kenyataan nanti, daya tahan imperium Amerika hanyalah akan berumur setahun jagung, tidak bisa menandingi imperium Romawi kuno yang berlangsung selama lima abad. Apalagi, jika disandingkan dengan imperium Turki Usmani atau imperium Sriwijaya yang bertahan selama tujuh abad.