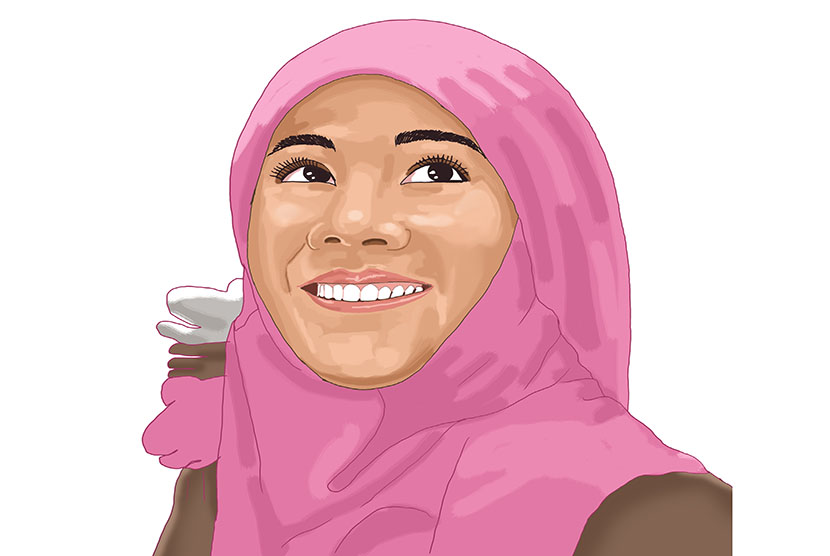REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Asma Nadia
Sedih, marah, bingung, kecewa, kaget, malu, heran, dan tidak mengerti.
Mungkin seluruh kata di atas masih belum cukup untuk menggambarkan perasaan yang terlukis saat mengetahui kebiadaban yang dipertontonkan dalam video tewasnya Haringga Sirila, pemuda yang dianiaya secara bejat, bahkan diperlakukan lebih buruk dari seekor binatang.
Manusia normal tidak melompat-lompat di atas binatang yang terkapar sekarat, tidak menusuk anus binatang yang sudah mati, tidak bergantian menendangi atau memukuli dengan benda keras secara sukacita meski terhadap hewan yang tidak mengganggu.
Memperlakukan hal serupa terhadap binatang jelas merupakan perilaku tidak beradab, apalagi ditujukan kepada sesama manusia. Sejujurnya, ungkapan biadab terasa belum sepadan, belum mewakili itu semua.
Saya sedih, hancur, membayangkan seorang anak yang ingin menonton bola, pulang hanya tinggal nama. Lebih dari itu, masih pula menyisakan kenangan mengenaskan yang pekat di batin orang tuanya.
Dua puluh tiga tahun lalu, kedua orang tua itu pasti menyambut kehadiran sang bayi, dengan mata bercahaya, dan senyum tersungging. Membayangkan bagaimana mereka memilih nama Haringga (yang menurut sebuah situs nama berarti pencerahan spiritual, karisma, dan lain-lain), merawat, lalu membesarkan.
Amat banyak kenangan indah yang telah dilukis ingatan, tentu kenyataan pahit yang kemudian terwujud bukan akhir yang pernah tebersit dalam benak ibu atau ayah mana pun.
Marah. Melihat pada tayangan video yang viral begitu melimpah khalayak lalu-lalang. Telinga mereka mendengar apa yang terjadi, tapi memutuskan tidak peduli.
Mata mereka melihat kekejaman yang berlangsung, tapi tidak mencegah. Bahkan, seorang pimpinan suporter mengatakan sempat melihat kejadian itu tapi berlalu, tidak bertindak. Walau dengan kapasitasnya, sangat mungkin sosoknya didengar dan dia mampu menghentikan.
Bingung. Mengapa setelah ada aksi pembantaian yang terjadi hanya beberapa meter dari stadion, pertandingan tetap dilangsungkan. Seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada penyesalan, tidak ada empati, tidak ada evaluasi.
Yang tersisa hanya ego dan kepentingan. Hitung-hitungan ekonomi. Jika ditunda, akan sulit mengadakan tanding ulang. Jika dibatalkan, panitia pasti harus mengembalikan uang tiket.
Padahal, kejadian ini mungkin masih bisa diantisipasi jika panitia pelaksana mau mendengarkan masukan dari kepolisian untuk tidak menyelenggarakan pertandingan pada hari libur, sehingga massa yang kecewa karena tidak kebagian tiket tidak membeludak, juga usulan kedua, agar menyediakan layar lebar untuk memecah keramaian.
Kecewa, sebab kita baru saja bangga dengan sportivitas anak bangsa di Asian Games. Bahkan, ketika begitu geram dengan keputusan wasit yang mencuri kemenangan timnas dengan penalti yang dianggap tidak layak, kita masih mampu bersabar.
Kaget. Ya, amat sangat tersentak menyaksikan ada belasan lebih anak manusia yang sanggup melakukan tindakan sedemikian bengis.
Ke mana nurani? Lunturkah rasa iba di hati, hingga jeritan pilu korban tidak menggugah kesadaran? Ke mana otak mereka diletakkan?
Apakah telah menguap sebab lama tidak dipakai untuk berpikir sebab terbiasa cuma berfungsi menggerakkan otot untuk melakukan tindak kekerasan? Lebih dari itu, tragedi ini terjadi di sebuah negeri, tempat bangsanya dikenal ramah, menjunjung kesopanan dan kesantunan, juga bermoral.
Malu. Sebagai anak bangsa, saya malu bahwa ada bagian dari kita, generasi muda, bisa melakukan kekejian yang setara dengan zaman jahiliyah, bahkan tak terusik sama sekali saat tertangkap kamera.