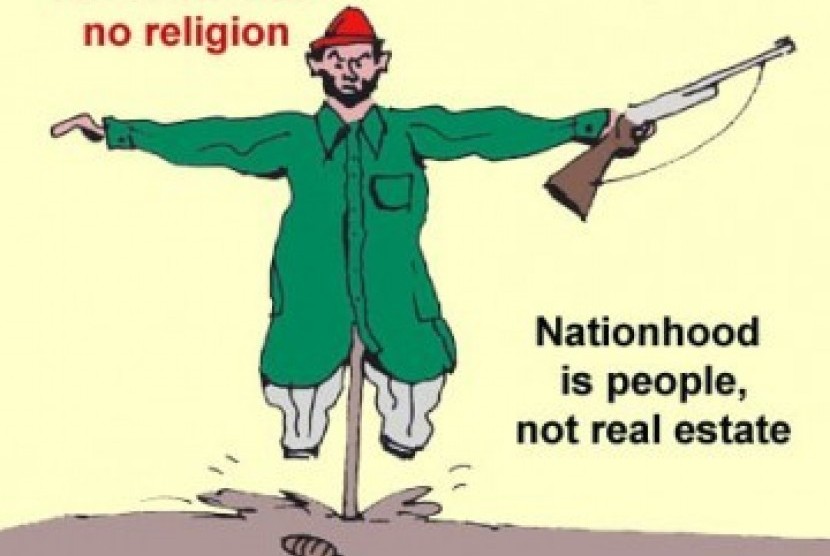REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Kun Wazis *)
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius pernah menegaskan bahwa saat ini (2017) tidak ada lini yang benar-benar steril dari radikalisme, termasuk dunia pendidikan. Pernyataan ini menarik disikapi secara kritis dengan mencermati dua hal. Pertama, dunia pendidikan, baik yang umum dan berbasis agama, memiliki potensi disusupi paham radikal dan teror. Sebagai contoh, pondok pesantren--sebagai lembaga pendidikan agama Islam tertua di Indonesia--berulang kali dikaitkan dengan isu radikalisme dan terorisme. Padahal, pondok pesantren yang jumlahnya mencapai 28.000 di nusantara, sama sekali tidak mengajarkan Islam radikal dan Islam teror, melainkan pendidikan Islam yang rahmatan lil alamin.
Kedua, mengokohkan peran institusi pendidikan Islam pondok pesantren sebagai benteng menanggulangi radikalisme dan terorisme di Indonesia. Sebab, dengan pengajaran agama Islam di pondok pesantren tersebut dapat menghapus fenomena radikalisme maupun terorisme atas nama agama. Kedua fenomena tersebut menjadikan peran strategis pondok pesantren dalam menahan laju perkembangan bibit-bibit “pemikiran keras” membumi dalam ruang pendidikan di tanah air.
Penting dikemukakan bahwa kekhawatiran terhadap isu terorisme atas pondok pesantren di Indonesia kembali disuarakan Wakil Presiden Yusuf Kalla (Wapres JK) pada penghujung Desember 2016 silam. Saat membuka Halaqah atau Pertemuan Ulama dan Pesantren Se-ASEAN di Bogor Jawa Barat (13 Desember 2016), Wapres JK mengingatkan kembali potensi ancaman isu tersebut dan meminta para ulama dan pesantren untuk menyebarkan ajaran Islam moderat untuk menangkal radikalisme dan terorisme.
“Permohonan” Wapres JK dihadapkan 120 perwakilan pesantren dari negara Malaysia, Brunei, dan Indonesia waktu itu menjadi sinyal penting merekatkan ukhuwah umat Islam melalui jaringan pesantren dalam menangkal globalisasi isu terorisme yang dikonstruksikan secara negatif untuk Islam dan umatnya. Sebab, pesantren memiliki seperengkat aset pendidikan yang luas, mulai tingkat RA/ TK, MI/ SD, MTs/ SMP, MA/ SMA, hingga Perguruan Tinggi (PT).
Kecemasan Wapres tersebut sebelumnya telah disuarakan oleh BNPT pada 02 Februari 2016 yang menyebutkan 19 pondok pesantren di Indonesia terindikasi menyebarkan radikalisme dan terorisme. Polemik mengenai isu terorisme terhadap pesantren tersebut berkembang “liar” dan menimbulkan perdebatan publik, karena penyebutan oleh BNPT pada saat itu hanya berselang sebulan setelah peristiwa teror bom Thamrin Jakarta (14 Januari 2016).
Berbagai berita dan opini saling berkelindan; ada yang pro dan ada yang kontra. Kelompok yang setuju melihat potensi isu tersebut bisa terjadi jika pesantren mengadopsi paham-paham yang non-ahlussunnah wal jamaah, sedangkan kelompok yang menolak berargumentasi bahwa sebanyak 28 ribu pesantren di Indonesia mayoritas mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin sehingga tidak mungkin memproduksi “ulama” yang berhaluan radikal dan teror. Berkaitan dengan isu radikalisme dan terorisme yang kembali “memanas” pada 2017 karena telah merasuki dunia pendidikan, maka pemahaman terhadap realitas isu tersebut menjadi penting agar kita tidak terjerumus dalam cara pandang yang justru dapat “meneror” pesantren yang mengajarkan Islam rahmatan lil alamin.
Pertama, gencarnya isu radikalisme-terorisme terhadap pesantren sering kali disebut media Barat. Sholeh (2007) menyatakan bahwa media Barat menyebut pesantren telah menjadi ‘breeding ground’ radikalisme dan terorisme di Indonesia. Menurut Zamroni (2005), sedikitnya, terdapat tiga pesantren--pesantren al Mukmin Ngruki di Surakarta, pesantren Al Zaitun di Indramayu, dan pesantren Al Islam di Tenggulung Solokuno Lamongan--yang disebut-sebut dalam diskursus Islam radikal di Indonesia versi Amerika.
Ketiga pesantren tersebut diduga menjadi sumber gagasan-gagasan untuk mendirikan negara Islam, menerapkan syariat Islam dan juga mengampanyekan anti-Amerika, sehingga memunculkan gerakan-gerakan teroris. Namun, sampai tahun 2017 ini, ketiga pondok pesantren tersebut melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa saja dengan “kurikulum pesantren” dan santrinya terus bertambah.
Perlu diketahui, kepentingan media massa Barat memaksakan definisi terorisme pernah dikritik keras Ilmuwan komunikasi Indonesia Deddy Mulyana (2008). Menurut guru besar Universitas Padjadjaran itu, media Barat, terutama Amerika, sering memaknai Islam sebagai agama primitif yang membenarkan perbudakan, poligami, harem-harem, penindasan wanita, kekerasan, dan terorisme. Para pengelola media Barat, baik cetak maupun elektronik, sering mengasosiasikan apa yang dilakukan oleh kaum Muslim sebagai representasi Islam, apalagi bila sang aktor adalah pemimpin muslim.
Dalam pandangan media Barat, apa yang dilakukan Saddam Hussein, Amrozi atau Imam Samudra adalah representasi Islam. Maka yang terjadi adalah pertarungan makna. Pemenangnya, bukan siapa yang benar, melainkan siapa yang berkuasa. Maka, tidak mengejutkan bila Amerika Serikat sebagai “Sang Tuan” dunia lewat media memaksakan definisinya sendiri mengenai tindakan apa saja yang termasuk terorisme dan siapa yang dapat dijuluki teroris.
Pemahaman seperti ini penting untuk disadari oleh umat. Dalam hal ini, dibutuhkan sikap kehati-hatian dalam mencermati isu tersebut dan tidak latah (ikut-ikutan) “menjustifikasi” lembaga pendidikan Islam pondok pesantren yang Islam rahmatan lil alamin sebagai “mesin pencetak” kader bangsa berhaluan radikalisme-terorisme. Sebab, akibat penjulukan negatif (negative labelling) tersebut, menurut Jainuri (2016) pada akhirnya stereotyping Islam sama dengan ideologi kekerasan selalu mewarnai berita-berita Barat dan belahan dunia non-Barat.
Jainuri mengutip hasil penelitian Media Tenor yang menyebutkan sembilan dari sepuluh berita yang disiarkan tentang muslim dan Islam di USA, Inggris, dan Jerman adalah terkait dengan perang atau terorisme. Dominasi opini di media massa tentang dugaan 19 pondok pesantren yang dituding berhaluan radikalisme dan terorisme akan menancap di benak wacana khalayak, dibandingkan dengan 28 ribu pondok pesantren “ahlussunnah” yang jarang mendapatkan tempat di media massa.
Kedua, globalisasi isu terorisme adalah bagian dari proxy war. Fenomena kedua ini diungkapkan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam berbagai kesempatan dengan menegaskan bahwa isu tersebut merupakan bagian dari perang proxy (proxy war)--kolonialisasi negara asing terhadap Indonesia dengan menggunakan pihak ketiga--untuk menjatuhkan citra Indonesia di mata internasional sehingga dapat menjadi alasan negara asing untuk menguasai Indonesia.
Bahkan, perang proxy tersebut ditempuh dengan cara membeli dan menguasai media massa untuk pembentukan opini, menciptakan rekayasa sosial, serta membuat kegaduhan di masyarakat. Pernyataan tersebut patut dikritisi mengingat sinyalemen Busro Muqoddas lewat karya bukunya “Hegemoni Rezim Intelijen: Sisi Gelap Peradilan Komando Jihad” (dalam Jainuri, 2016) mengungkapkan bahwa aksi terorisme di negeri ini adalah konstruksi intelijen negara sendiri. Hal ini dibuktikan bahwa kelompok radikal Islam yang direkrut menjadi teroris kemudian melakukan pengeboman adalah buatan intelijen. Menurut dia, intelijen menciptakan suasana yang menyudutkan kalangan ekstremis Islam. Mereka didiskriminasi agar timbul kebencian kemudian diprovokasi untuk membentuk negara Islam di Indonesia.
Dua hal tersebut penting untuk disikapi agar sebagai bangsa kita tidak menjadi “gelap” karena isu radikalisme dan terorisme terhadap dunia pendidikan pondok pesantren dapat menimbulkan dampak yang besar di tengah-tengah masyarakat. Pertama, dalam konteks ini, isu terorisme dan radikalisme terhadap pondok pesantren di Indonesia yang dikonstruksi oleh kekuatan kapitalisasi media massa akan menjadi wacana dan sikap negatif masyarakat terhadap pondok pesantren.
Padahal, institusi pendidikan agama Islam tersebut selama ini mengajarkan Islam rahmatan lil alamin, jauh dari bahasa kekerasan. Dalam jangka panjang, jika tidak ada wacana tandingan, maka khalayak dapat membenarkan realitas negatif terhadap institusi pesantren di masa yang akan datang. Dan, itu sangat berbahaya, mengingat pondok pesantren adalah lembaga pendidikan khas Indonesia dan secara empiris terbukti mampu mendidik umat dengan akhlaqul karimah di berbagai pelosok negeri.
Kedua, dengan menyadari bahwa isu terorisme adalah bagian dari proxy war yang digunakan negara lain untuk menguasai Indonesia, maka kita perlu bersikap kritis juga terhadap isu yang dilontarkan pihak-pihak tertentu terhadap kekuatan umat Islam di lembaga pendidikan pondok pesantren di Indonesia. Hal ini dapat ditempuh dengan terus melakukan tabayyun (cek dan ricek), menjalin silaturahmi antar ulama dan kyai pesantren, membangun paradigma Islam melalui berbagai kegiatan dengan melibatkan banyak pihak, sehingga isu negatif tentang Islam dan umatnya di pesantren dapat sejak dini dikenali dan dicegah penyebarluasannya.
Lebih dari itu, karena radikalisme dan terorisme adalah bentuk pemaksaan paham yang mengajarkan kekerasan, maka kekuatan para ulama-kiai pesantren, ustad, dan para santrinya adalah modal utama dalam upaya penyadaran kepada umat terhadap ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan melibatkan para ulama-kiai, ustad, dan santri dalam membangun kontrol ajaran di pesantren, maka isu-isu sesat yang sejenis, seperti radikalisme, ekstremisme, fundamentalisme, dan militanisme yang “berbau” stereotip negatif dapat ditangkal secara lugas dan tuntas. Sebab, Islam yang diajarkan di pesantren bukanlah radikalisme maupun terorisme. Tentu saja, peran media massa dalam mengonstruksikan realitas isu tersebut akan sangat penting dalam ikut serta membangun masyarakat yang damai di bumi nusantara.
*) Dosen IAIN Jember, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran.